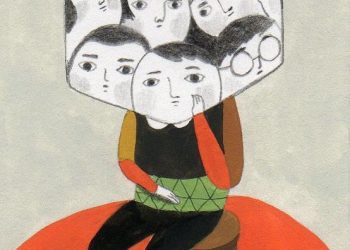Bahasa Sunda secara tidak langsung mempunyai segudang nilai-nilai didaktik dalam kehidupan, baik itu pandangan hidup, nilai filosofis, nilai moralitas, maupun nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut banyak terkandung di dalam babasan dan paribasa Sunda, atau di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “ungkapan” dan “peribahasa”.
Dalam kajian linguistik, ungkapan (babasan) didefinisikan sebagai kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Sedangkan peribahasa (paribasa) adalah kelompok kata atau kalimat (frasa dan klausa) yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan sesuatu (Ramdani, 2021:39).
Sebagaimana kita tahu, di zaman sekarang telah terjadi pengikisan karakter di dalam tubuh masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Sunda. Pengikisan karakter tersebut terjadi di seluruh tatanan sosial kehidupan masyarakat.
Salah satu dampak yang paling dominan dan terasa adalah pengaruh negatif terhadap sikap dan perilaku masyarakat, di antaranya adalah sikap individualisme, hedonisme. Namun yang paling memprihatinkan adalah mulai jarangnya penggunaan bahasa Sunda di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam ruang lingkup formal maupun non-formal.
Penggunaan bahasa Sunda di dalam ruang lingkup formal sempat menjadi polemik tatkala salah satu anggota DPR-RI mengkritisi seorang Jaksa Agung menggunakan bahasa Sunda di dalam sebuah forum rapat, yang kiranya tidak semuanya rapat itu berjalan seluruhnya menggunakan bahasa Sunda, melainkan hanya beberapa idiom-idiom bahasa Sunda saja yang muncul, semisal sampurasun, kumaha damang dan lain sebagainya.
Pengikisan dan polemik tersebut dipicu oleh pengetahuan tentang bahasa Sunda dan jarangnya pemakaian bahasa Sunda di dalam kehidupan sehari-hari. Berkaca kepada kasus tersebut, muncul akibat dari susahnya mempelajari bahasa Sunda.
Anggapan ini banyak bertebaran di masyarakat, mengingat adanya eufemisme di dalam bahasa Sunda itu sendiri yang dikenal masyarakat Sunda sebagai penghalusan bahasa atau undak-usuk atau tingkatan tuturan di dalam menggunakan bahasa Sunda, yang masuk ke dalam etika menggunakan bahasa.
Meski begitu, kesulitan dan kerumitan tersebut menjadikan bahasa Sunda sebagai bahasa yang unik. Tidak mudah untuk membedah dan meneliti bahasa Sunda, dikarenakan banyaknya problem dan paradigma yang bertebaran di masyarakat, seperti keragaman bahasanya (dialek, idiolek, kronolek, dll.). Di samping hal-hal tersebut, ada unsur yang sangat menarik untuk dikaji, yakni babasan dan paribasa.
Babasan dan Paribasa: Permainan dan Alat Sindir
Bagi masyarakat Sunda umumnya, babasan dan paribasa ini tentunya sudah tidak asing lagi. Berdasarkan maksud yang dikandungnya, menurut Ramdani (2021:40) babasan dan paribasa ini terdiri atas; wawaran luang (informasi pengalaman), pangjurung laku hadé (perintah untuk berbuat kebaikan), dan panyaram lampah salah (pencegah untuk berbuat kesalahan).
Bila dilihat dari uraian tersebut, sangat relevan untuk menjadi salah satu sarana pengedukasian mengenai pendidikan karakter masyarakat Sunda, khususnya di dalam penggunaan bahasa Sunda.
Munculnya babasan dan paribasa di dalam masyarakat Sunda tidak terlepas dari kebiasaan orang Sunda yang lebih senang “permainan” bahasa sebagai alat untuk “menyindir” atau memberitahu tentang suatu hal dengan cara yang halus tanpa menyakiti perasaan orang lain.
Keduanya muncul dari hasil kebudayaan masyarakat Sunda dalam pakeman-pakeman atau konvensionalitas bahasa atau ungkapan-ungkapan masyarakat Sunda terdahulu (Sutisna, 2015:2). Dari paparan tersebut, secara tidak langsung orang-orang terdahulu (leluhur) masyarakat Sunda telah melakukan pendidikan karakter yang di mana aspek bahasa sebagai sarana pengedukasiannya.
Mengacu kepada standar etika masyarakat Sunda dalam tataran sosial tergambarkan dengan beberapa babasan dan paribasa, berikut ini sekurang-kurangnya ada dua belas babasan dan paribasa hasil dari inventarisasi pribadi, seperti:
- Soméah hadé ka sémah (berperilaku baik kepada tamu).
- Amis budi (ramah; bahasanya santun dan murah senyum).
- Datang katingali tarang, undur katingali punduk (jika pergi, tidak begitu saja; pamitan lebih dahulu ketika akan pergi seperti ketika datangnya).
- Dihin pinasti anyar pinanggih (segala hal yang terjadi sekarang sesungguhnya sudah ditakdirkan lebih dulu oleh Tuhan).
- Disakompétdaunkeun (disamaratakan, tidak dipisah-pisah).
- Élmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna (hidup harus menuntut ilmu untuk keselamatan dunia akhirat, serta harus hidup sederhana).
- Genténg-genténg ulah potong (walaupun hasilnya tak seberapa, tidak apa-apa daripada luput sama sekali; walaupun sakit parah, semoga saja jangan sampai meninggal dunia, mudah-mudahan bisa sembuh seperti sedia kala).
- Hadé gogog hadé tagog (baik budi bahasanya, baik sikapnya; tahu adat dan sopan santun).
- Hampang birit (rajin; giat).
- Handap asor (mau menghargai atau menghormati orang lain).
- Hérang caina beunang laukna (berhasilnya apa yang kita inginkan tidak lantas menimbulkan akibat buruk bagi orang lain atau tidak menimbulkan konflik).
- Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat (keselamatan serta kebahagiaan seorang anak tergantung kepada ridho dan doa ayah ibunya.
Dari babasan dan paribasa hasil inventarisasi tersebut sangatlah relevan sebagai sarana untuk mengedukasi pendidikan karakter masyarakat Sunda, apalagi dikomparasikan dengan pembelajaran bahasa Sunda baik itu di tingkat SD-sederajat, SMP-sederajat, serta SMA-sederajat bahkan sekalipun di perguruan tinggi.
Di samping pengkomparasian dengan lembaga pendidikan formal, babasan dan paribasa juga bisa juga dikaitkan dengan norma-norma etika yang berlaku di masyarakat Sunda umumnya. Dalam masyarakat Sunda, ada bererapa cara melakukan pendidikan karakter untuk menghasilkan masyarakat yang masagi paripolahna (baik dalam kehidupannya; bertutur kata dan perbuatannya), seperti pendekatan kerohanian; agama.
Untuk menyampaikannya, diperlukan unsur untuk menjadi sarananya. Babasan dan paribasa bisa dijadikan sarana, berkaitan dengan penyampaiannya. Sebagai contoh, babasan dan paribasa:” indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat” dan hadé gogoh hadé tagog”.
Kedua contoh ini bila dilihat dari maknanya mengandung nilai-nilai keagamaan, karena ridho Tuhan ada di ibu dan ayah; keselamatan serta kebahagiaan seorang anak tergantung kepada ridho dan doa ayah ibunya (contoh 1) dan seorang manusia harus baik di dalam perilaku dan bertutur kata untuk mewujudkan manusa yang berakhlakul karimah (contoh 2).
Sebenarnya, babasan dan paribasa ini tak terhitung jumlahnya, dipengaruhi pemakaian, perkembangan bahasa, dan ragam bahasa (dialek) di dalam bahasa Sunda itu sendiri.
Pendidikan karakter yang dimana babasan dan paribasa sebagai sarananya akan terwujud apabila penggunaan bahasa Sunda di masyarakat masih tetap eksis. Eksistensi bahasa Sunda sendiri tergantung kepada masyarakatnya, apakah masih memiliki kesadaran atau tidak. Karena “lamun ilang basana, tangtu ilang bangsana”. Cag! Hurip Sunda![]