Karena Metafor.id ini website dengan kelas jangkauan internasional, maka ada baiknya sebelum saya membalas bacotan Cak Jabbar, saya jelaskan dulu peta geografis silaturahminya agar para pembaca Metafor.id yang multi-nasional ini sedikit bisa memahami kalau ada dua kera berkelahi soal musik.
Cak Jabbar mungkin orang yang kalau pergi ke kondangan ketika ambil lauk prasmanan lupa melepas lilitan tisu pada sendok dan garpunya: ujug-ujug ambil nasi, daging, dan sayur. Tisunya ikut basah kena sayur dan nasi. Akhirnya ia aduk sekalian saja daripada malu.
Maksudnya, beliau pasti orang yang tergesa-gesa. Memangnya Metafor.id cuma milik orang Jogja, hei? Ada Joachim Loew di Jerman dan Stevie Wonder di Amerika Serikat yang mungkin saja menjadi pembaca setia salah satu rubrik di website ini. Maka jelaskan dulu asal muasalnya. Katanya lulusan pondok pesantren Darul Ulum, masa tidak mengerti konsep “asbabun-nuzul”. Wkwkwk.
Saya tukang asah-asah di kedai kopi Kapeo Pekalongan. Cak Jabbar ini barista Syini Kopi. Kita sebut saja “Barista” supaya dia punya sedikit kebanggaan untuk diceritakan ke anak-cucunya kelak. Walaupun sebenarnya barista itu ya selevel dengan kuli batu. Kerja, berkeringat, lalu dibayar. Bedanya barista lebih amis lambenya (untuk tidak menyebutnya ndakik/kemaki) dalam urusan kopi dan lebih klimis-narsis pilihan citranya di media sosial. Sementara kuli batu cuma paham bagaimana bekerja maksimal hari ini agar orang di rumah bisa makan.
Saya dikenalkan dengan Cak Jabbar lewat Mas Nopal yang mbahureksoni website ini. Perkenalannya di Syini Kopi Jogja. Waktu itu saya sedang dolan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu saya berkontak via WhatsApp dengan Cak Jabbar. Kemudian iseng-iseng punya ide untuk mengisi waktu luang di sela sepinya warung kopi musim hujan untuk semacam bikin tulisan-tulisan ngehek seputar warung kopi, dimulai dari playlistnya. Karena kebetulan penghulu perkenalan kami, Mas Nofal, punya website Metafor.id, ya sudah, kami sepakat untuk mberakin hasil tulisannya di sini.
Jadi begitu kurang lebih latar belakang dari adegan surat menyurat saya dengan Jabbar. Bagaimana, tidak penting bukan? Ya memang tidak penting. Saya juga fake saja. Biar disangka punya unggah-ungguh. Padahal orang sudah tidak kenal unggah-ungguh. Bansos yang “Ban”-nya berarti “Bantuan” saja, dananya disunat 10 ribu perak per paket kok, terus kita bicara unggah-ungguh? Malu sama cicak.
***
Kalau politik bengkok, seni yang meluruskannya, kata John F. Kennedy. Lah, repot-repot amat. Mak Erot saja tidak pernah sok menjadi hero dengan cara meluruskan penis yang bengkok. Kok seni ini nranyak mau meluruskan politik bengkok? Lagi pula Tuhan juga pasti sudah matang dalam mengonsep kehidupan. Ada yang memang ditakdirkan menjadi bengkok, ada yang ditakdirkan untuk lurus. Jadi kalau Indonesia hari ini bengkok, mungkin memang sudah takdirnya seperti itu.
Begitulah, Cak Jabbar, sedikit kepongahan seni. Jadi jangan terlalu lebay sama musik. Sampai-sampai The Beatles lagunya dimaknai. Waduh, Beatles dimaknai, kitab suci disinisi. Hehe. Nyuwun sewu, The Beatles itu bukannya band yang nyontek Tielman Brothers milik Indonesia Timur itu ya? Sedangkan kalau mau komparasi, Beatles jelas tidak lebih keren dari Rolling Stones, sorry to say. Hahaha.
Tapi kalau sampiyan memaksa saya menginterpretasikan John Mayer, itu sudah dari jaman awal Corona saya menuliskannya. Coba mampir ke website saya, masuk ke Corona Apocalypse nomor 31. Atau saya beri saja satu puisi saya yang mencatut nama John Mayer. Walaupun menurut Cak Jabbar saya tidak tampan-tampan amat, tapi saya dikit-dikit bisa lah kalau cuma nulis puisi abal-abal:
Gravitasi Blues
Gravitasi di dalam ruang puisi sedang mabuk, dan aku tak butuh John Mayer. Aku belum berlutut pada seluruh kesembronoan di trotoar. Atau kepada iuran BPJS yang jungkat-jungkit, cermin birokrasi yang gemar merebus kembang trompet dan meminum kuahnya bersama mie instant. Mungkin aku ngantuk, tapi bantalku penuh dengan Stevie Ray Vaughan, atau Jimmi Hendrix, pokoknya “Little Wing” (perlu sayap supaya tidur tidak bocor). Berisik sekali. Batas antara subuh dan fajar menjadi sepanjang surat Al-Baqarah. Sapi, sapi, sapi. Wirid lenguh sapi. Berliter-liter susu sapi kukocok dalam uap bertekanan algoritma rumit. Hasilnya: semiotika gemetar dalam secangkir cafelatte yang gelap dan dangkal. Kujamin rasanya tetap enak karena setiap kali kau meneguknya, secambuk knalpot RX-King ikut memacu adrenalinmu yang mulai linglung oleh beragam headline news tentang situasi ekonomi nasional. Enterpreneurship pasca pandemi, mitologi digital marketing, santet oligarki, tenung startup, sihir dan mantra-mantra kapitalisme global. Bergoyang-goyang di jidatmu. Sementara di jidatku, Blues Crossroad masih mencari jalan untuk bertegur sapa dengan sepi ruang dan senyap waktu.
Gravitasi Blues, simsalabim!
bulan, laut, kangen, dan air
telah kering di dalam panci yang mendidih.
Kajen, Juli 2020.
***
John Mayer memang seorang guitar virtuoso. Album “Continuum” saya akui sebagai salah satu album fusi slow rock-blues terbaik. Juga sebagai musisi, ia cukup menguasai banyak spektrum genre secara teknis-teoretik. Bahkan sebagai gelombang, fender stratocasternya itu bisa masuk ke banyak wilayah. Bisa masuk ke HipHop (stel: Jay Z feat. John Mayer – D.O.A). Bisa ke Jazz (stel: Alicia Keys feat. John Mayer – Ain’t No Sunshine / Shawn Mendes feat. John Mayer – Where Were You in The Morning). Atau Neo Soul (stel: Leon Bridges feat. John Mayer – Inside Friends). Bisa juga Pop-Rock (stel: Keith Urban feat. John Mayer – Sweet Thing). Bahkan ia juga pernah collabs dengan mendiang Steve Jobs di markas Apple.
Segan ya? Mungkin. Mungkin iya sebagai artist cum guitarist. Cuma masalahnya John Mayer ini kecut untuk menyentuh isu-isu sosial. Apalah artinya lengking-lengking bending, bila terpisah dari derita lingkungan. Apalah artinya strumming, bila terlepas dari masalah kehidupan. Kepadamu, aku bertanya! Loh kok jadi Rendra.
Ya soalnya setahu saya, selain nomor “Belief” dan “Wanting on The World to Change“, Mz John kurang vokal terhadap isu-isu konkrit. Kurang “punk”. Padahal musikalitasnya berakar pada Blues. “Blues is the roots, everything else is the fruits“, sedap. Dan Blues berakar pada ketertindasan orang-orang kulit hitam yang bekerja sebagai petani kapas. So?
Ya tapi biarlah. Memang siapa juga yang mewajibkan musisi melek isu-isu sosial? Memang musisi mesti nyambi jadi SJW?
Musisi tidak wajib merangkap fungsi sebagai aktivis sosial. Kalian ini mau mendengar bunyi, nada, dan irama, atau pidato UNICEF? Sementara kalau Bob Marley melahirkan “Jamming” dari konteks sosial politik apartheid, anggaplah itu bukan termasuk wilayah tema musik, melainkan sekadar urusan kuliner sejarah.
Begitu, Cak, sedikit soal John Mayer. Bagus, tapi tidak sespesial martabak telur tiga. Selebihnya, untuk urusan customer ukhti-ukhti itu, saya punya cerita yang lebih menarik soal segmentasi customer Kapeo secara keseluruhan.
Tapi santai saja dulu, ambil napas, silakan disruput kopinya. Boleh sama pisang goreng Syini. Boleh sama live instagramnya idola sampiyan, Pepeng: imam besar jama’ah kopi light roast, yang kemarin miwir-miwir karena tanaman Monsteranya hilang dicuri orang. Wkwkwk.
Imam besar kok masih bisa dibikin sedih oleh kehilangan. Ada-ada saja drama tukang kopi. Sama kualitasnya dengan drama termehek-mehek milik anak Pak Presiden, ibarat lukisan: “jelek saja belum”. Telenovela paling tengik saja bahkan tidak semenjijikkan itu.[]
Tanjung Kulon, Maret 2021







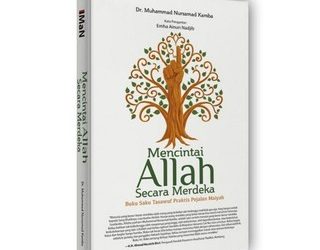









Comments 2