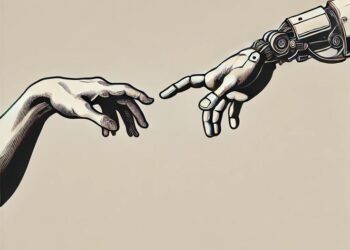Tentu, di benak kita pernah terlintas sebuah pemikiran nakal, misalnya “Wujud an sich Allah itu seperti apa?”, “Seperti apa jika kita bersemuka dengan Allah, seperti dua orang yang sedang berbicara atau bagaimana?”, dan masih banyak pertanyaan nakal lainnya. Menurut saya, sah-sah saja apabila seorang beriman bertanya demikian. Dengan berpikir tentang Allah, seorang beriman sedang ingin mengenal secara mendalam Siapa yang ia sembah. Bukankah ada peribahasa “tak kenal maka tak sayang”?
Frasa wahdatul wujud terbentuk dari dua kata: “wahdat” yang berarti satu atau kesatuan dan “wujud” yang berarti esensi. Maka, wahdatul wujud berarti kesatuan wujud. Umumnya, seorang beriman percaya bahwa Allah adalah “Al-Haq” alias Sang Kebenaran. Allah yang adalah Sang Kebenaran dapat dikenal dengan banyak cara, misalnya merenung-hayati alam semesta. Dalam tradisi mistik Kristiani, terdapat pula konsep demikian. Bonaventura—salah seorang pengikut Fransiskus dari Assisi—mengatakan bahwa iman, yang adalah sebuah peziarahan jiwa, kepada Allah dapat sungguh-sungguh dihayati dengan memandang pewahyuan-Nya yang nyata melalui alam (natura est vestigium Dei, alam adalah tapak-tapak Allah).
Alam menjadi salah satu cara untuk mengenal Allah. Cara demikian merupakan sebuah tradisi yang ada di hampir semua agama. Cara mengenal Allah yang demikian ini memiliki potensi ke arah panteisme, sebuah paham yang melihat bahwa esensi Tuhan dapat ditemui dalam alam semesta. Konsep demikian yang oleh agama-agama Abrahamik umumnya dipandang ‘berbahaya’, karena akan mengganggu pemahaman tentang esensi Tuhan yang Mahasuci, berada di surga, memiliki batas dengan dunia manusia yang fana, dan sebagainya. Nurudin Al-Raniri, seorang ulama Aceh yang menghayati kemuslimannya dengan konsep yang mirip panteisme justru dianggap menyimpang dari prinsip Tauhid.
Satu konsep lain yang menghantar manusia untuk mengenal wahdatul wujud Allah adalah Manunggaling Kawula Gusti. Konsep yang lahir dari agama-agama bumi—di mana Yang Ilahi tidak ditemukan jauh mengawang-awang di luar sana, melainkan selalu sudah hadir di dalam hati orang-orang yang percaya kepada-Nya—kemudian ‘dipinjam’ sebagai sebuah konsep beriman dalam agama-agama Abrahamik. Dasar dari konsep ini terdapat juga di dalam agama-agama Abrahamik, di mana penyerahan diri kepada Allah dan Allah yang menanggapi keluh kesah manusia. Dalam istilah familiar, itu disebut juga sebagai doa, cara manusia berkomunikasi dengan Allah.
Dalam “Manunggaling Kawula Gusti”, roh manusia bersatu dengan Roh Ilahi dalam penyembahan. Kesatuan antara manusia dengan Allah bukan terjadi di tingkat jasad, melainkan di alam roh, di mana materialisme ditinggalkan. Dan yang terjadi tinggal “Solo Dios basta” (“Hanya Tuhan, cukup”), apabila kita ingin mengutip dari pengalaman mistik Teresia dari Avilla yang juga memiliki pengalaman “Manunggaling Kawula Gusti”.
Selain konsep panteisme, wahdatul wujud Allah juga dapat dikenal dengan cara lain. Konsep al-muwahhid misalnya, sebuah konsep yang meneguhkkan prinsip Tauhid. Konsep yang lahir dari pemikiran Ibn ‘Arabi ini mau mengatakan bahwa Allah tercermin pada alam dan alam adalah cerminan Tuhan. Esensi Allah secara an sich tidak sama dengan alam, namun sifat-sifat-Nya dapat kita kenal di alam semesta.
Bagi Ibn ‘Arabi, alam terdiri dari tingkatan-tingkatan, seperti jamadat (benda padat), nabatat (tumbuhan), hayawanat (hewan), insaniyat (manusia), dan malakut (malaikat). Wujud semua yang ada ini pada hakikatnya adalah wujud Allah yang dipinjamkan kepada semesta. Konsep ini juga dapat kita temukan dalam tradisi Kristiani. Bagi Bonaventura, alam adalah “vestigium Dei” (‘tapak-tapak’ Allah) di mana seluruh atribut-Nya—Mahabaik, Mahapenyayang, dan sebagainya—dapat kita temukan di alam semesta.
Selain konsep al-muwwahid, Ibn ‘Arabi juga menggunakan penjelasan matematis untuk membuktikan esensi Allah. Bilangan-bilangan, yang banyak dan terbatas, berasal dari satu sumber (dengan pengulangannya). Bilangan sendiri ada karena ada yang dibilang. Walaupun bilangan itu berasal dari satu sumber, namun setiap unit bilangan adalah realitas mandiri. Jadi, “yang banyak” berasal dari “Yang Satu”, dan “yang banyak” berada dalam tegangan antara ‘mandiri’ (berdiri sendiri sebagai sebuah realitas), namun juga berasal dari “Yang Satu” (karena membawa nilai-nilai dari “Yang Satu” ini).
Sama seperti hukum matematis, demikian pula Ibn ‘Arabi menalar Allah melalui cara pikir yang metaforis (majaz). Menurut saya, alur pemikiran Ibn’ Arabi ini justru banyak meminjam konsep dari Plotinos tentang pemikirannya akan “Yang Satu”.
Pola pikir mendasar mengenai wahdatul wujud adalah tajalli al-haq (penampakan diri Sang Kebenaran). Secara umum, agama-agama Abrahamik menyebut ini sebuah pewahyuan, di mana Dia yang awalnya tidak kita kenal, lantas memperkenalkan diri dengan pewahyuan. Bagi Ibn ‘Arabi, wahyu bukan hanya teofani (penampakan Tuhan dalam wujud nyata), melainkan fayd (emanasi, meminjam konsep filsafat Yunaninya Plato), zuhur (pemunculan, penampakan, kelahiran), tanazzul (penurunan), dan fath (pembukaan).
Nantinya, Ibn ‘Arabi membedakan antara isi pewahyuan (esoteris) dan ‘kulit’ pewahyuan (eksoterik). Di wilayah esoteris, Ibn ‘Arabi memiliki konsep kesatuan. Segala pencarian agama-agama tentang Yang Ilahi bermuara pada Sang Esa. Pengalaman mistik menjadi jalan utama mengenal Sang Esa, karena pengalaman mistik merupakan sarana non-dualistik, tanpa bentuk, dan tanpa kejamakan. Jalan pengalaman mistik menjadi jalan paling tepat untuk menjumpai Sang Esa. Namun, di wilayah eksoterik, Ibn ‘Arabi melihat bahwa manusia akan “menginstitusikan” jalan untuk mencari Sang Esa, yang oleh Ibn ‘Arabi ditemukan dalam Islam sebagai sebuah kesempurnaan jalan.
Bagi saya, Ibn ‘Arabi—dan para mistikus lain—selalu mau memurnikan jalan sebuah agama yang terkadang justru lebih nampak sebagai sebuah institusi daripada sebuah pencarian iman. Melalui pemikiran mistikus, kita diajak mencari Sang Esa dengan ketulusan dan kemurnian. Hanya dengan jalan demikian, kita dapat menjumpai Pribadi Sang Esa tersebut pada Diri-Nya, karena kita sudah lepas dari dualisme diri.
Semangat “bersemuka dengan Allah” inilah yang digali kembali. Jangan sampai, agama hanya sebatas sebagai polisi moral yang lepas dari kenthos (pokok biji)-nya, yakni membawa orang “menemukan Dia di dalam aku dan aku di dalam Dia”. Agama harus membuat ‘anak-anak’ yang bernaung di bawahnya melihat sosok Allah sebagai Pribadi yang tremendum et fascinosum (menggetarkan dan memukau). Semoga![]
Sumber Bacaan:
Nurcholish, Ahmad – Alamsyah M. Dja’far. 2015. Agama Cinta: Menyelami Samudera Cinta Agama-agama. Jakarta: Elex Media Komputindo.