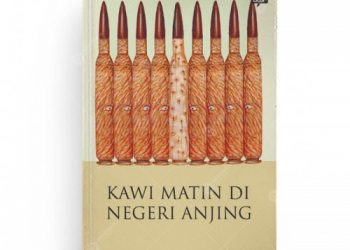Seperti kebanyakan suami lainnya, Hadwan mengemas letihnya setiap sehari untuk dibawa pulang bersama rindunya kepada istri. Ia dapati langit sore itu berwarna jingga tatkala dirinya menanggalkan sepatu pantofel dari kedua kakinya. Duduk di teras rumah sudah menjadi kebiasaannya setahun terakhir. Termangu menunggu istri yang akan ia saksikan berjalan dari ujung gang. Datang dari suatu tempat, yang menurut wanitanya itu disebut sebagai kebahagiaan.
Bekerja. Kebahagiaan yang disebut istrinya adalah bekerja. Dengan bekerja ia mendapatkan kebebasannya sebagai seorang wanita. Tidak dikekang. Tidak juga dikurung dalam status yang telah mengubahnya sekarang: ibu rumah tangga. Meski begitu, menikah menjadi satu pilihan terbaik yang datang dari masa depan. Begitu mekar hati Hadwan saat mendengar pernyataan itu langsung dari bibir istrinya, di hari pertama meresmikan ikatan cinta; senang tiada kira. Sampai detik ini, itulah alasan mengapa dirinya memaklumi belahan jiwanya agar mempertahankan kebahagiaan yang dibangun semenjak duduk di bangku kuliah.
Hadwan melayangkan telapak tangan kanannya ke dahi. Baru ia ingat jika ibu memang menelepon istrinya kemarin. Lalu, mengatakan bila hari ini akan berkunjung. Untuk mengantarkan sekeranjang kue lapis kesukaan Nuria, istrinya.
“Pukul berapa istrimu pulang,Wan?” Wanita itu berdiri di depan pintu menanyakan keberadaan Nuria yang belum terlihat.
Hadwan pun menjawab, “Sebentar lagi, Bu,” tanpa menyerongkan wajahnya karena sibuk menghitung burung kuntul yang beranjak ke peraduan.
Wajah murka ibu kini terpancar saat ia menyelesaikan keasyikannya menghitung tadi. Sepertinya ibu marah, simpulnya dalam hati.
Ia mengekor di belakang. Mengikuti perintah yang wanita itu buat dengan jari telunjuknya.
***
Hadwan rasa ruang tamu menjadi ruang terbaik yang ia punya. Pasalnya, pada ketinggian dua meter di dinding pucat itu terpajang potret sepasang pengantin baru nan berbahagia. Tersenyum ke arah kamera. Kemudian abadi dalam figura. Dan selalu menjadi obat pelipur lelah. Di sana tercetak wajah Nuria yang ceria. Entah mengapa sore ini justru hawanya begitu dingin. Mungkinkah karena tatapan ibu yang tajam? Tatapan yang sudah menjadi tabiat ibu kalau sedang marah.
“Mengapa istrimu tidak mengancingkan bangle dan gunting kecil ini di bajunya?”
Kali ini dugaan Hadwan tidak meleset.
Tidak ia sangka ada bangle kecil yang tergeletak di atas meja. Bersebelahan dengan segelas teh manis yang Nuria minum pagi tadi.
“Boleh jadi Nuria kelupaan, Bu. Tadi pagi istriku kesiangan dan buru-buru,” terangnya mencari alasan supaya keganjilan ini tidak memicu hal yang fatal.
“Bukankah ini sudah yang kedua kalinya istrimu meninggalkan bangle sembarangan?” tanya ibu penuh selidik, matanya melirik sebelum mengambil tumbuhan berwarna kuning tersebut. “Ingat, Hadwan! Istrimu itu tidak sendirian. Ada calon anak kalian yang harus dirawat dengan baik. Ya, salah satunya dengan mengancingkan bangle ini. Demi keselamatan ibu dan bayinya.”
Hadwan terbungkam. Mendengarkan perkataan ibu yang diulang-ulang di setiap kesempatan. Apalagi ini tentang kepercayaan yang bertolak belakang antara ibunya dan Nuria.
Kepercayaan yang dibangun orang dulu terhadap bangle, gunting kecil lipat, dan peniti. Ketiga benda itu dikenakan pada pakaian wanita yang sedang mengandung. Tujuannya, agar si ibu dan bayi dalam kandungan terhindar dari mala petaka yang tidak diinginkan. Itulah mengapa wanita paruh baya itu sangat perihatin kepada menantunya. Sudah sibuk bekerja pulangnya lewat petang hari pula. Konon menjelang magrib pantangan bagi ibu hamil berkeliaran di luar rumah. Jilakau kondisinya seperti Nuria, ibu anak dua itu yakin bangle sangat membantu keselamatannya.
“Baiklah. Kalau begitu Ibu pamit. Jaga selalu istrimu dengan baik, Nak.” Akhirnya ibu memutuskan untuk pulang. Setelah meninggalkan pesan bagi Hadwan.
***
Pukul 17.15 WIB. Nuria sampai rumah. Wajah lesunya dapat Hadwan saksikan dari sofa tempat pria itu sedang duduk.
Usai mengucap salam dan melepas alas kaki, Nuria menyusul suaminya duduk di sofa. Berpandang-pandangan sebentar sebelum akhirnya berpelukan. Tak lama dari itu, ia menemukan keranjang cokelat di dekatnya.
“Kue lapis ini dari Ibu ya, Kang?” tanya Nuria setelah mencari tahu isi keranjang tersebut.
Hadwan cuma mengangguk. Tidak minat berbicara ketika pikirannya semrawut begini.
“Sayang banget, aku enggak bisa ketemu Ibu di hari kerja. Minggu besok kita gantian ke rumahnya ya, Kang.”
Sekali lagi Hadwan cuma mengiyakan.
“Ibu pulang naik apa tadi?” Nuria mulai gusar mengamati reaksi suaminya.
“Terminal cukup ramai angkutan umum ke arah rumah, Sayang. Ibu naik ojol dari sini,” katanya tanpa maksud bernada tinggi.
Padahal menurut Hadwan istrinya lumayan paham rute menuju rumah ibu. Jika dimulai dari rumah yang mereka tempati saat ini, ojeg online sudah bisa diakses dengan mudah, setting lokasi tujuan. Setelahnya, ibu turun di depan gang. Lebih-lebih lokasinya tidak jauh dari bahu jalan. Jadi, ia tidak terlalu risau, meskipun ibu dituntut keluarkan tenaga untuk berjalan sekitar kurang lebih sepuluh meter lagi.
Sayangnya, Nuria telanjur sebal. “Kamu enggak bisa bicara pelan pada istrimu? Aku kaget, Kang!” Serunya memberi jarak duduk yang agak berjauhan sebagai peringatan.
“Maafin Akang, Dek. Akang kaget ketika Ibu tahu kamu nggak bawa bangle.”
“Bangle?” Tanya Nuria penuh selidik.
“Ya, rempah bangle ini.” Hadwan menggenggamnya dengan perasaan yang resah.
Nuria tampak tidak berdaya. Kesal juga bila harus membahas masalah ini sepulang kerja. Singkatnya, ia capek jika harus berdebat masalah bangle. Atau rempah yang dikenal bernama zingiber cassumunar itu. Khasiatnya memang banyak, tergantung pemanfaatan dari rempah itu saja: mau ditujukan untuk apa.
Sejak kabar kehamilannya terdengar, ibu juga lekas menyiapkan gunting kecil lipat yang dikaitkan pada peniti. Sepaket dengan rempah bangle yang dipercaya sebagai bentuk perlindungan. Bukan. Bukan dari segi medis. Akan tetapi, dari sudut pandang orang tua yang menjadikan penangkal dari segala pantangan. Utamanya mengacu pada persoalan gaib. Banyak yang bilang, kepercayaan ini tumbuh agar mendapat keselamatan. Membuat Nuria yang hamil agak kurang nyaman mengancingkannya di setiap setelan seragam yang ia pakai.
“Itu karena agak mengganggu penampilanku, Kang. Yang paling pentingnya, kamu juga tahu kalau gunting dan peniti bisa menimbulkan luka tusuk,” katanya membeberkan alasan-alasan yang sekiranya masuk akal. Sekaligus mengingatkan kembali perihal tragedi yang dialami oleh tetangganya sendiri.
Sembilan bulan yang lalu kira-kira, tetangganya yang hamil itu terkena infeksi akibat luka sayat yang semakin hari semakin menjalar. Dokter bahkan menyampaikan bila lukanya terindikasi virus sehingga mengakibatkan tetanus.
Lagi pula tidak ada dampak yang terjadi bila bangle itu terpasang di sela-sela kemeja dan tanda pengenalnya. Baginya terasa kolot. Tidak diterima oleh akal pikirnya.
Merasa belum tuntas, Nuria kembali mengutarakan, “Cukup perusahaan saja yang memiliki banyak aturan. Tapi, kamu suamiku, Kang. Aku mohon beri aku kesepakatan, bukan aturan yang membuatku tertekan.” Seketika wanita berbadan dua itu bungkam. Harap-harap cemas menunggu reaksi dari Hadwan.
“Berhenti bekerja saja kalau begitu!” Titah pemuda itu.
Dingin yang semula menyelimuti ruang tamu sekejap sirna, memanas oleh penyangkalan Nuria. “Tidak, tidak akan aku biarkan seseorang merusak kebahagiaanku. Aku ingin terbebas dari pemikiran yang kolot, Kang. Pemikiran yang hanya berputar pada larangan-larangan saja. Tanpa kejelasan dari tujuan larangan itu dibuat.”
“Berhenti membangkang, Nuria! Patuhi saja apa yang dikatakan suamimu!” Hadwan menggenggam tangan Nuria erat-erat, “Aku mampu membahagiakanmu, tanpa membiarkanmu letih bekerja. Kamu mau ‘kan, Sayang?”
Nuria langsung mengelak, “Selama kesepakatan itu belum ada, aku tidak akan patuh pada peraturan yang masih janggal. Aku ini memang perempuan. Bukan berarti dengan bersuami, aku tidak bisa menciptakan kebahagiakanku sendiri.”
“Sudah keterlaluan kamu!”
Sebuah tamparan nyaris saja menjerat Hadwan sebagai lelaki yang tiada lagi punya harga diri.
***
Hadwan tidak kuasa mendengar istrinya tersedu-sedu semalaman. Itu pasti tidak nyaman baginya setelah bekerja seharian. Nuria juga jadi susah makan. Hanya satu kue lapis yang masuk ke mulutnya kemarin. Sisanya wanita itu hanya diam.
Dan ia putuskan untuk melonggarkan toleransi pada istrinya kembali. Sebelum ia menutup pintu rumah dari luar dan berangkat bekerja.
“Kamu harus minum ini dulu,” pintanya sambil menyodorkan susu jahe yang tadi pagi ia buat.
“Ini apa?” tanya Nuria lirih.
“Susu jahe, Sayang. Bukan hal-hal aneh seperti yang kamu pikirkan. Jadi, sekarang kamu minum, ya. Biar badanmu enggak kedinginan.” Nuria pun meminumnya selagi Hadwan membenarkan jaket yang ia kenakan.
Cuaca sepagi ini tidak biasanya bikin badan terasa beku.
“Aku minta maaf soal masalah kemarin. Tidak bermaksud sedikit pun Akang menyakitimu.” Hadwan tidak membiarkan Nuria kedinginan sampai harus mendekapnya erat. “Kamu benar. Kita hanya butuh kesepakatan. Apalagi soal menghargai ibu yang masih menjunjung tinggi kepercayaannya itu.” Hadwan menjeda, lalu mengakhirinya dengan keputusan bahwa, “Kamu boleh tidak mengenakannya selama itu membuatmu nyaman. Aku hanya memintamu supaya selalu menjaganya, meskipun cuma disimpan di dalam tas.”
“Tumben kata-katamu manis, Kang.” Nuria mempertanyakannya dalam lirikan yang menggoda.
“Bukankah setiap harinya aku memang manis?” Kini Hadwan balas menggodai istrinya.
“Halah, gombalmu itu memang tak ada tandingannya. Paling top nomor satu!” Tangan Nuria tak sampai hati mencubit gemas perut suaminya.[]