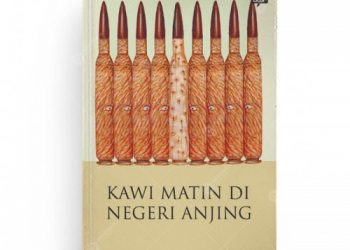Selama satu jam, saya telah duduk di depan meja mungil kamar. Dengan cahaya mentari, angin-angin silih bergantian hilir mudik melalui jendela satu-satunya di kamar. Beberapa bulan yang lalu ketika sepulang kerja shift siang–sekitar pukul 10 malam–jalanan Bandung diselimuti awan hitam ditambah hujan rintik-rintik membasahi jalanan malam itu.
Saya mengendari “doc” motor kesayangan saya dan ayah, membelah rintik hujan yang satu per satu tetesnya menusuki wajah saya. Malam itu tak banyak orang ada di jalan, selain karena dinginnya minta ampun, isu Covid-19 yang kian santer terdengar membuat orang-orang lebih memilih menarik selimutnya.
“Doc” telah terisi penuh bahan bakar saat itu, saatnya saya yang mengisi bahan bakar: makan. Gerai-gerai minimarket sudah tutup, para tunawisma mulai membuat api kecil dari sampah untuk menghangatkan badan. Satu per satu jalan di bawah rindangnya pepohonan Kota Kembang saya lewati.
Saya memarkirkan “Doc” di sebelah warung pecel lele dan buru-buru masuk karena hujan semakin deras. Sambil saya duduk rehat, Mas Koki warung ini menyodorkan minuman pembuka berupa teh hangat. Sejenak saya menyulut rokok untuk menghangatkan badan sambil telapak tangan saya yang kedinginan memeluk gelas.
Sekilas warung pecel ini tak beda jauh dengan warung pecel lele yang lain. Spanduknya sama, minuman pembukanya sama segelas teh tawar hangat, dibalut sekeliling kain dengan gambar menu yang disediakan. Tentunya juga di bawah terpal berwarna biru, yang melindungi saya dan Mas Koki dari rintik hujan.
“Pesan apa mas?” Ucap Mas Koki itu, meski dia tak menggunakan celemek atau topi koki. Ia hanya menggunakan topi dan jaket yang kentara dengan nuansa Italia.
Saya memesan pecel lele. Oh iya, bila cuaca dingin, orang-orang mulai mencari kehangatan; ada yang merokok, ada yang menarik selimutnya, memeluk pacarnya atau sekadar minum kopi atau teh. Namun menurut saya, menghidupkan obrolan pun salah satu cara menghangatkan dari dinginnya malam.
“Mas, kenapa warungnya dinamakan La VR 46?” Saya memulai obrolan.
Dia tertawa, sambil membolak-balik lele pesanan saya di wajan.
“Saya nge-fans Mas, sama Valentino Rossi. Ya beginilah cara saya.”
Saya lupa cerita satu hal: ada banyak pedagang pecel lele dan ayam goreng, ratusan bahkan mungkin ribuan, namun baru saya sadari hanya ada satu warung yang berbeda. Iya, warungnya dapat kamu temui di perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Dan warung pecel inilah alasan saya menulis tulisan ini.
Pada umumnya warung-warung pecel lele dan ayam goreng diberi nama-nama yang biasa saja, seperti “Seafood Cak Ado” atau yang lainnya. Karena dari nama saja sudah berbeda dan cukup unik, jadi saya haqqul yaqin warung ini lebih dari sekadar warung pecel lele–karena menyimpan banyak cerita di dalamnya.
Ngomong-ngomong pecel lele pesanan saya sudah jadi. Si Mas koki mematikan kompornya, lalu menyulut rokok kretek dan duduk di depan meja saya. Sambil saya makan, ia mulai bercerita dari mana ia berasal, kekhawatiran ia tentang Covid-19 hingga terutama dan yang paling utama adalah “perjalanan hidupnya”.
Mas Koki ini kalau saya tebak umurnya belum terlalu tua, palingan akan masuk ke usia kepala 5. Sampai pecel lele habis ia masih terus bercerita, sementara saya sibuk mendengarkan dan mengolah-ngolah ingatan agar tidak lupa jika sudah sampai di rumah.
Nuansa kental negeri Pizza tercium dari pecel lele yang digoreng si Mas Koki. Selain nama warung “LA VR 46” yang berarti “Valentino Rossi”, ia juga penggiat sepak bola Italia. Ditambah malam itu mas Koki ber-outfit ala Italia. Topi dan jaketnya itu salah satu klub asal Italia dan yang mungkin terlewat, spanduk pecel lelenya berbendera negeri yang terkenal dengan Coloseum-nya itu. Inilah semua yang mengabsahkan bahwa ia blasteran Italia dan Lamongan.

Saya jadi kepikiran, nampaknya dalam kultur game saat ini ia sudah menyandang status “Mythic” karena ia telah hampir 14 tahun malang-melintang berkecimpung di dunia makanan kaki lima. Selain kembali mengisi teh hangat saya yang sudah bocor, ia menawari rokok ke saya–sebuah bukti keramahan pribumi jika menyangkut soal ngobrol.
Sama seperti kamu jika mengidolakan seseorang, tentu suatu hari ingin bertemu dengan idolamu. Si Mas Koki juga sama. Ia bermimpi menonton Valentino Rossi saat menjelang masa pensiunnya sebagai pembalap profesional.
“Ketinggian ga sih Mas? Tukang pecel lele nonton di sirkuit? Hahaha.” Begitulah ujarnya.
Mungkin kedengarannya olok-olok, Tukang Pecel Lele bermimpi menonton idolanya balapan di Sirkuit. Tapi si Mas Koki bukan sekedar pemimpi yang kerap asik dengan dunia mimpinya. Ini berbeda, akhirnya saya tau jika ia sungguh-sungguh ingin menonton karena ia bilang, ia rutin menyisihkan sedikit demi sedikit uangnya dari sejuta keperluan hidup ini, demi suatu hari nanti menonton idolanya di Sirkuit Mandalika Lombok.
Yang membikin saya terkesan dari si Mas Koki ini adalah mimpinya yang terus ia kejar meskipun banyak kewajiban yang musti ia penuhi–menafkahi istri dan membiayai pendididikan anak-anaknya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, ia menuturkan bahwa penghasilan dagangannya merosot, sementara kebutuhan makin meroket.
Sama seperti saya, kamu atau mungkin jutaan pribumi di Nusantara yang terdampak virus Covid–19. Si Mas Koki bercerita soal minimnya bantuan pemerintah sementara ia harus berjuang mati-matian agar usahanya tidak gulung tikar dan dapur rumahnya tetap bisa “ngebul”. Meskipun dengan segudang permasalahan yang terjadi, tetap saja negeri ini tak pernah kehabisan cerita-cerita di dalamnya.
***
Di samping semua cerita itu, saya ingin lompat sedikit. Bahwa saya menyukai sepak bola. Mulai dari bercerita, mengulik-ngulik kisah di luar lapangan, menuliskannya sampai mungkin yang paling sering saya lakukan: datang nonton ke stadion. Wabil-khusus sepak bola, telah banyak membantu saya dalam hal apapun.
Mungkin kamu belum menyadari jika di Indonesia, sepak bola telah menjadi hajat banyak orang. Saking banyak dan besarnya, kamu akan menyadari jika klub sepak bola telah menjadi identitas suatu daerah. Malahan menjadi identitas dari mana orang itu berasal.
Misalnya, saya berasal dari Bandung, orang-orang akan tau atau menilai seketika jika saya pendukung Persib Bandung, bukan Persija Jakarta. Begitupun kalau kamu datang dari Makassar, maka jelas darah “PSM Makassar” mengalir deras dalam nadimu.
Hal yang sama juga ada dalam diri si Mas Koki. Ia lahir di kota Lamongan dan ada darah “Persela Lamongan” di nadinya. Meskipun ia telah lama pergi merantau ke Bandung, tak lantas membuat si Mas Koki menjadi pendukung Persib. Darah dan hatinya tetap untuk Persela Lamongan.
Ngomong-ngomong soal Tukang Pecel Lele nih, si Mas Koki bilang bahwa kebanyakan mereka datang dari Lamongan. Si Mas Koki bercerita bahwa dulu saat “Persela” sedang mengalami kesulitan finansial, para Tukang Pecel Lele ramai-ramai urunan atau patungan untuk membantu meringankan beban finansial itu.
Sejak saya tau cerita tersebut, saya jadi sadar betapa berharganya klub sepak bola atau sepak bola itu sendiri. Si Mas Koki juga bilang, ia dan kawan-kawan seprofesinya tak pernah muluk–muluk ingin melihat Persela juara. Cukup dengan adanya Persela di laga kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia pun, ia sudah bersyukur katanya.
Cerita-cerita si Mas Koki tentang kota kelahirannya, tentang kota yang membesarkannya dan tentang kota tujuannya ketika kulitnya semakin berkeriput, cukup banyak memberi inspirasi kepda saya. Boleh jadi bahkan ia mungkin berniat menjadikan Lamongan sebagai kota yang akan menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Seakan menyiratkan makna bahwa:
“Seorang bocah bisa pergi dari Lamongan, tapi lamongan akan tetap tinggal dalam tubuh si bocah”
***
Kini malam hampir larut. Semuanya basah dan kabut melayang di atas jalanan dalam bentuk sulir putih. Sudah waktunya saya pulang dan si Mas Koki mulai membereskan dagangannya.
Seluruh dunia tenggelam dalam larutnya malam, dan aku tidak mendengar banyak kendaraan berlalu-lalang pada malam itu. Setelah saya membayar, si Mas Koki kemudian ikut mengantar ke motor saya.
“Hati-hati di jalan Mas. Kapan-kapan mampir lagi ya…“ Tegurnya ramah.
Saya mengucapkan terima kasih dengan lembut ke Mas Koki dengan jabatan dua telapak tangan yang kedinginan. Lantas berjalan pergi menembus kabut.
Hujan membasahi tengkuk saya, sesudah beberapa saat saya lupa menanyakan namanya. Tapi bodo amat dia pun tak bertanya nama saya. Pada Malam itu kami berdua bercerita banyak hal. Mungkin terlalu panjang jika saya tulis semuanya. Untuk sisa obrolannya, kamu perlu mengunjungi si Mas Koki secara langsung, di depan tugu batas Kota Bandung dan Cimahi. Ia selalu membuka tenda warungnya setiap pukul 17.00 sampai 23.00 WIB. Silakan mampir kalau sempat.