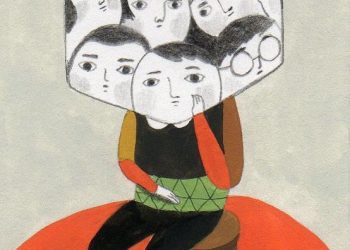Sebagai basis kebudayaan dan peradaban manusia, pendidikan menempati peran yang tidak sepele. Pendidikan sejatinya berposisi sebagai proses pengasuhan, pembimbingan, dan pengembangan potensi individu melingkupi aneka aspek—baik jasmani, budi pekerti, dan penalaran. Dari sini dapat kita perluas bahwa pendidikan bukanlah urusan yang hanya melibatkan sekolah dan institusi an sich. Lebih dari itu, ia bisa ditempuh di mana saja, diserap dari siapa saja, dan dikenyam dalam momentum yang variatif.
Namun satu fakta yang miris: semenjak roda globalisasi bergulir ke segala penjuru, ditambah dengan kehadiran media baru digital, watak manusia modern ikut terpengaruh oleh keduanya. Kita menjadi semakin terisap oleh derap zaman yang bermental industrial: harus serba-teratur, mekanis, dan predictable (Solihin, 2004). Di tengah menjamurnya gedung pencakar langit dan pesatnya teknologi informasi kontemporer, manusia dilanda infodemic. Darinya muncul pusparagam gejala anomali dan titik-balik psikologis. Manusia modern mengalami keterasingan. Kegersangan spiritual (Burhani A.N, 2002). Tidak kaget jika dari sinilah mereka tergerak untuk menyelami kembali dimensi adikodrati ruhaniah—sebagai bentuk counter wave.
Mencermati fenomena tersebut, tentu akan ada titik temunya dengan khazanah pendidikan psikosufistik yang hendak mendekati manusia secara utuh (holistic). Tidak hanya menggamit unsur intelektualitas (IQ) semata, namun juga anasir emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Dalam ungkapan sederhana, pendidikan psikosufistik berupaya mencerna dan memaknai pelbagai tindakan, fenomena, realitas dan aktivitas pembelajaran dengan kesadaran luhur. Mentransendensikan segala aspek untuk kemudian didayagunakan sebagai instrumen penjinak hawa nafsu—yang mana beragam kecenderungan negatif dan merusak dapat muncul karenanya.
Jika meminjam frasa Emha Ainun Nadjib, penting bagi kita kalangan muda untuk memilih dengan pertimbangan matang antara tiga hal: “menduniakan akhirat”, “mengakhiratkan dunia”, atau “mendunia-akhiratkan kehidupan”. Yang pertama, menduniakan akhirat adalah bentuk ‘profanisasi’ hal-hal yang sakral sehingga akan mudah terjerembab ke dalam sekularisme dan merubah nilai-nilai luhur menjadi sesuatu yang permukaan dan kemasan. Kedua, mengakhiratkan dunia sudah lumayan baik, namun masih mengandung sikap dikotomis, tidak lengkap, parsial—segala urusan di dunia dimaknai akhirat semata.
Sedangkan yang terakhir, mendunia-akhiratkan kehidupan menjadi pilihan yang seimbang dan akan lebih potensial menuju keharmonisan hidup. Bahwa dalam hidup ini, semisal, nikmat perzinahan itu urusan dunia, dan tidak perlu diakhiratkan karena sudah jelas dosa. Juga keperluan sholat dan puasa itu urusan akhirat sehingga tidaklah bijak jika dipolitiki demi keuntungan duniawi. Mengacu dari ulasan ini, kita dapat memilih titik pijak dan sikap mana yang akan dapat mengantarkan kita ke dalam kebahagiaan yang asli. Bukan kebahagiaan semu yang cuma berlangsung sesaat. Ephemeral pseudo-happiness.
Identifikasi Kecerdasan Spiritual
Dalam proses mendedikasikan diri ke dalam medan pendidikan yang holistik sebagaimana di atas, otomatis memerlukan serangkaian instrumen dasar untuk menyukseskannya. Terutama dalam urusan ruhaniah, keberhasilan spiritual adalah hasil perpaduan dari menangnya akal dan kalahnya hawa nafsu (Nurbakhsy, 2000). Bahwa kalah dari ego—sehingga terjebak menjadi anak buahnya—akan memicu kita melakukan aneka bentuk tindakan yang senewen dan serampangan. Dengan kata lain, ketelatenan dan kegigihan untuk menjinakkan potensi destruktif dalam internal diri kita sangatlah penting.
Ikhtiar untuk menjinakkan nafsu ini, salah satunya, dapat dimulai dengan rajin bermuhasabah. Introspeksi diri sekaligus evaluasi multiaspek yang berlangsung dalam diri kita beserta tindakan keseharian. Dari muhasabah, seseorang akan terlatih untuk menilai diri sendiri secara adil. Mengetahui mana sikap (attitude) dan perilaku (behavior) kita yang negatif, dan mana yang baik dan mendatangkan manfaat.
Apabila sudah rutin melakoninya, maka sebagai tahap lanjutan atau alat identifikasi ke orang lain, kita dapat membaca beberapa poin dari Danah Zohar dan Ian Marshall di bawah ini tentang karakteristik umum dari kecerdasan spiritual.
- Kemampuan bersikap fleksibel.
- Memiliki kecerdasan tajam dan produktif.
- Cerdas menyikapi penderitaan.
- Sanggup mengatasi rasa takut dan khawatir.
- Pandangan hidup berorientasi nilai dan visi besar.
- Tidak menyimpan niat untuk berbuat kerusakan.
- Kerap menemukan keterkaitan pelbagai peristiwa, aspek, urusan, dan hal-hal apa saja secara utuh dan Ilahiah (adikodrati).
- Sering bertanya “mengapa” dan “bagaimana”.
- Punya potensi menjadi pemimpin yang berdedikasi dan tulus mengabdi.
Dari serangkum uraian di atas, setidaknya bisa kita cermati ke diri kita sendiri apakah sudah memiliki beberapa poin tersebut atau belum sama sekali. Apabila belum, maka sudah waktunya bagi kita mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita ketahui. Sebab, seperti kata orang Jawa, ilmu kelakone kanti laku. Ilmu itu berlangsung dan semakin maksimal diperoleh justru di saat kita menerapkannya ke dalam perbuatan.[]
Sumber Bacaan:
Burhani, Ahmad Najib ed. (2002). Manusia Modern Mendamba Allah. Jakarta: Penerbit Iman & Hikmah.
Nurbakhsy, Javad. (2000). Psychology of Sufism (penerj. Arief Rakhmat). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
Nadjib, Emha Ainun. (2014). Tuhan pun Berpuasa. Jakarta: Kompas Gramedia.
Solihin, M. (2004). Terapi Sufistik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Zohar, Danah & Ian Marshall. (2007). SQ: Kecerdasan Spiritual. Bandung: Mizan Pustaka.