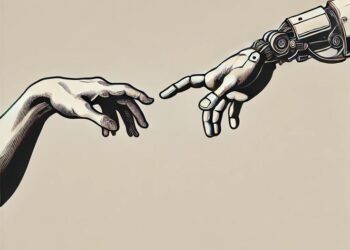Selama ini, apabila seseorang―bisa juga beberapa orang―membicarakan genduren, pasti nggak akan jauh-jauh dari kata bid’ah. Entah bagaimana ceritanya, topik genduren ini rasanya seolah sangat sempit―hanya seputar ia bid’ah atau bukan. Padahal, bila kita mau mengulasnya lebih detail, ada banyak hal yang bisa dibicarakan dari genduren. Misalnya, kasta emak-emak rewang. Saat ini, kasta tertinggi emak-emak rewang masih dipegang oleh golongan yang memiliki kemampuan menanak nasi pulen dalam jumlah yang banyak. Tak semua orang mempunyai kemampuan unik tersebut. Oleh sebab itu, di daerah saya golongan ini biasanya sudah ditentukan dan diberi pesangon oleh shahibul hajat (tuan rumah).
Kasta kedua dipegang oleh golongan yang memiliki kemampuan memasak serundeng. Sama seperti golongan sebelumnya, golongan ini juga tak sembarang orang bisa mengisinya. Kasta kedua ini seolah punya resep rahasia yang bisa menyulap rasa serundeng menjadi begitu khas. Namun, perlu dicatat bahwa pembagian kasta ini berdasarkan realita yang terjadi di daerah saya, lho, ya. Bisa jadi di daerah Binjai beda lagi tingkatan kastanya. Kendati demikian, kita nggak bisa menafikan begitu saja peran lain dalam rewang. Tetap saja, harus diakui bahwa semua peran itu penting. Antara satu dengan yang lain saling melengkapi, seperti kita. Iya, kita! Kita berdua Indonesia. Nggak nyangka, ternyata implementasi Bhinneka Tunggal Ika bisa teridentifikasi dari kegiatan rewang.
Oke! Kembali ke genduren. Sebenarnya, esensi genduren itu sangat sederhana. Ia merupakan kegiatan doa bersama yang diakhiri dengan pembagian berkat. Namun, belakangan genduren sepertinya terlihat sedikit rumit, khususnya bagi penyelenggara. Pertama, terkait jumlah undangan. Mungkin hal ini terasa sepele, tapi nyatanya tidak. Jumlah undangan tentunya berusaha disesuaikan dengan tingkat ekonomi shahibul bait. Bila terlalu banyak, takut dananya nggak cukup. Bila terlalu sedikit, takut dikira memutus tali silaturahmi terhadap orang yang nggak diundang. Oleh sebab itu, perlu diambil jumlah undangan yang paling sedikit mudharat-nya. Hal ini kadang harus melalui proses diskusi yang tak sebentar. Maka, tak heran bila shahibul bait telah memutuskan mengundang berapa orang meski hari-H genduren terbilang masih agak lama.
Kedua, suguhan. Sebenarnya ini merupakan hak yang sepenuhnya dipegang oleh shahibul bait. Ia bebas mau menentukan jenis suguhan apa saja. Nah, justru kebebasan ini yang acap kali membuat bingung shahibul bait. Kebingungan tersebut pada gilirannya melahirkan sebuah fenomena yang cukup unik, fenomena yang terjadi dalam semesta emak-emak. Biasanya ketika sang Suami pulang dari genduren akan diberi pertanyaan, “Tadi suguhannya apa?”. Entahlah, apakah hal tersebut dijadikan sebatas referensi atau malah kompetisi bagi para emak, saya sendiri kurang mengerti detailnya.
Ketiga, berkat. Secara etimologi kata “berkat” (mungkin) asalnya dari kata barokah. Definisi barokah sendiri ialah ziyadah al-khair (bertambahnya kebaikan). Makna tersebut sangat relevan dengan realitas sosial yang terjadi pada berkat itu sendiri. Ya! Jamaah genduren sudah disuguhi makanan satu piring, ketika hendak pulang mereka masih diberi tambahan pemberian dalam bentuk berkat. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa kata “berkat” merupakan akronim dari “Lak wis bar, diangkat” (jika sudah selesai, diangkat). Ya iya lah diangkat, masa mau diseret?
Ada aturan khusus ketika kita hendak mengisi sebuah berkat. Misalnya, bila kita nylameti orang yang telah meninggal, maka jajanan yang semestinya dihadirkan adalah apem. Sependek yang saya dengar, penamaan “apem” ini bukan tanpa alasan. Kata “apem” lahir karena lidah orang Jawa dahulu tidak bisa mengucap kata ‘afwan (ampunan). Jadi, kehadiran apem dalam berkat tersebut merupakan representasi doa mohon ampun dari yang hidup kepada Allah, diperuntukkan bagi yang telah meninggal. Mungkin hal itulah yang membuat apem tak pernah hilang dari peredaran berkat, bentuknya sekarang malah cukup variatif.
Lain halnya dengan jajanan lain. Di era revolusi industri 4.0 ini, standar berkat telah jauh berubah. Dan, hal ini menjelma sebagai salah satu kompleksitas yang harus dihadapi shahibul bait. Banyak hal dari berkat yang bertransformasi. Transformasi ini kemudian memicu sebuah aturan baru, aturan tidak tertulis yang membuat persepsi masyarakat menjadikannya sebagai standar. Misalnya, dahulu wadah berkat adalah takir yang banyak lubangnya. Tapi sekarang beda, sekarang wadahnya pasti baskom. Bukan hanya wadahnya saja, sampai jenis kreseknya pun juga terjadi perubahan—mungkin lebih tepatnya peningkatan—.
Hal berikutnya yang juga mengalami perubahan adalah jajan. Sekarang, jajan selalu dibungkus dalam mika ukuran 2a. Jenis jajannya apa saja? Harus variatif pastinya, pokok pie carane mika kui kudu kebek. Saat ini, Teh Gelas dan wafer masih menempati posisi terfavorit untuk mengisi kekosongan mika. Dua makanan tersebut nggak pernah ada dalam berkat ketika saya masih kecil dulu. Bahkan, jika shahibul bait sedang malas membuat jajan atau nggak mau ngerepotin jamaah rewang terlalu jauh, berkat cukup dilengkapi hanya dengan wafer seharga Rp5.000. Jadi, emak-emak yang rewang nggak perlu bikin jajanan buatan sendiri.
Walhasil, era revolusi industri 4.0 ternyata nggak cuma mempengaruhi kehidupan dalam bidang teknologi industri dan digitalisasi. Era termaktub nyatanya juga mempengaruhi realitas sosial yang lekat dengan kehidupan agraris. Mungkin bisa disimpulkan bahwa era revolusi industri 4.0 menciptakan era revolusi berkat 4.0.