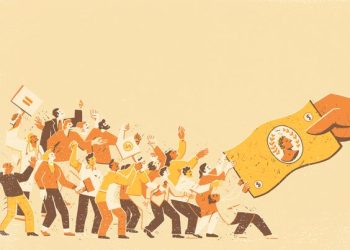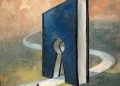Kapan terakhir kali kita menjenguk suatu peternakan? Atau minimal mengintip ke dalam kandang hewan ternak yang berisi satu kontingen keluarga saja. Bagaimana kondisinya? Seperti apa manajemen, pemosisian peran, tata-kelola kekeluargaan di dalamnya? Harmoniskah hubungan binatang ternak dengan pemiliknya?
Tidak harus kau jawab sekarang. Lantas setelah mencuripandangi perihal ternak secara visual-imajinatif, adakah terlintas di benak masing-masing kita tentang kemiripan ‘peradaban ternak’ di kandang dengan wajah situasi negara kita, bahkan dunia belakangan ini—beserta komplikasi silang-sengkarut konstelasi di dalamnya?
Banyak centang-perenang kerumitan zaman yang semakin hari makin absurd perwujudan tingkah-polahnya. Jangan-jangan kita sendiri yang membikinnya rumit dan absurd. Atau, malahan kita yang sedang teperdaya oleh pusparagam make-up terkini dan aneka riasan ber-merk mutakhir yang semakin canggih memoles dan mematut-matut penampilan? Syukurnya, mayoritas orang pada titik koordinat psikologis tertentu, pasti akan pernah memetik kesadaran: bahwa segala aspek di dunia ini tengah dicengkeram oleh ‘ideologi peternakan’ dan ‘dramatika industrialisasi’.
Tidak terhitung sudah berapa aspek dan ranah kemanusiaan yang diternakkan, dengan ribuan atau mungkin jutaan manusianya yang dijadikan SDT-nya. Sumber Daya Ternak. Sebab, yang konon disebut-sebut dan dibangga-banggakan sebagai SDM, seperti sindir Mbah Nun (Emha Ainun Nadjib), toh hanyalah ukuran yang parameternya disandarkan pada tingkat daya-produktivitas perorangan yang memberikan benefit kepada industri di mana ia bekerja. Bukankah yang demikian itu tergolong ‘mental ternak’?
Sekalipun seseorang tersebut memiliki produktivitas yang lumayan, selama ia tidak menyumbang keuntungan terhadap kepentingan industrial, maka ia tidak akan pernah dikategorikan sebagai SDM yang baik.
Apalagi, jika kita mentadabburi ungkapan Mbah Nun: “Kejahatan adalah nafsu yang terdidik. Kepandaian sering kali adalah kelicikan yang menyamar. Adapun kebodohan, acapkali, adalah kebaikan yang bernasib buruk. Kelalaian adalah i’tikad yang terlalu polos dan kelemahan adalah kemuliaan hati yang berlebihan.”
Ghiroh atau spirit keilmuan bangsa kita sekarang ini lebih mengutamakan hasil yang sekiranya dapat mendatangkan ‘daging-daging’ ilmu yang laku di pasaran (mainstream) dan ‘kotoran-kotoran’ hasil olah metabolisme dan sistem ekskresi yang bisa dijual sebagai pupuk. Pokoknya yang menghasilkan keuntungan dan kepuasan semu. Pseudo-satisfaction. Dengan sorot mata yang silau akan iming-iming omong kosong motivasional dan serapah janji cerah masa depan yang bagai cenayang seakan mampu memproyeksikan masa depan dari telunjuk jari mereka sendiri.
Silakan diamati pula, umpamanya, frame beternak sarjana. Kaum intelektual dijujui, disuapi dengan asupan gizi palsu yang kebak tabungan penyakit degredatif dan dekadensi bagi generasi mendatang. Atau, fenomena cendekiawan dan ulama yang menurunkan derajatnya—untuk menyebut: jual diri—agar memeroleh kursi empuk, bernama kedudukan. Selepas lulus, asal colak-colek, langsung calik (Sunda: dapat ‘duduk’).
Akan tidak ajaib jika muncul pertanyaan: masih adakah ilmuwan yang nir-belenggu syahwat keduniawian?
Karena kini, sosok begawan seakan sudah punah. Langka. Jika pun ada, akan dimatikan fungsi hidupnya, dihimpit peluang pergaulannya, dan masyarakat diracuni sedemikian rupa melalui broadcast fitnah, papan reklame iklan perendahan (baik daring maupun luring), dan propaganda kelas tengu untuk segera membencinya, membuangnya, mencampakkannya.
Sayangnya, begawan sejati tidak akan pernah benar-benar mati. Ia mengedari udara dan cakrawala, membagi-bagikan “hidangan kesejatian” yang dipetik dari samudera hikmah. Kewaskitaan cahyawi. Namun kenyataan yang sulit ditolak pada era ini adalah cahaya sering kali dimaterikan. Cahaya dikandangi untuk lantas diperjualbelikan—nu penting untung, Bos.
Juga tentang keterbalikan penghormatan masyarakat; dari urutan “orang baik, alim-sholeh, pintar, orang kuat, orang kaya, dan orang kuasa” sekarang berubah skala prioritasnya menjadi “orang kaya, kuasa, pandai, kuat, dan baik di titik terakhir”. Hal tersebut kontras betul dalam peradaban manusia postmodern ini—mungkin jika tak dibenahi, boleh jadi hingga pascapostmodern dan seterusnya.
Betapa tidak geleng-geleng kepala generasi kita yang sadar akan hal itu. Bahkan sebagian ada yang sampai menangis, sehingga dipanggil ‘generasi gembeng’ (Jawa: cengeng). Tidak jarang yang sekadar nepak tarang hungkul (Sunda: menepuk jidat) atau malahan ada yang sampai gereh-gereh (histeris). Terlebih jika menengarai peristiwa ‘pesta bisnis ternak ilmuwan’ yang dipelihara habis-habisan hanya demi dipenggal urat nadi kerohaniannya di hari esok.
Dan saat sudah sadar pun, tidak sedikit dari mereka yang menghibur diri lantas menyangkal, “Aih, kan dulu saat Nabi Isma’il diqurbankan Ayahandanya, Baginda Ibrahim, ia langsung diganti domba. Siapa tahu kita pun akan mengalami hal itu jua.”
Kemudian suara lain menimpali, “Sudahlah, hidup hanyalah antrean menuju penyembelihan. Tidak perlu terlalu risau.” Lalu ada tambahan yang di sandingnya, “Toh, Mbah Chairil sudah benar, hidup hanya menunda kekalahan. Sekali berarti sudah itu mati.”
Kebingungan pun menjejali para anak Adam di zaman now. Atau kita sama-sama hanya sedang berpura-pura bingung dalam dunia yang cuma tempat singgah meneguk air secawan ini? Ataukah kita mendadak blank karena kehabisan dialog saat melakonkan teater dengan skrip “ternak ilmuwan” ini?
Daripada hulang-huleung teu paruguh (melamun tak jelas), mending kita tinggal ngopi. Sambil sesekali bas-bus roko’an di beranda warkop dan suit-suit kalau ada cewek cantik lewat. Setidaknya dari situ kau terbukti bahwa masih seorang lelaki normal. Eh, jangan, ding—nanti salah-salah kau bisa dipidanakan karena sekarang cat-calling alias suit-suit ke cewek itu pelecehan.[]