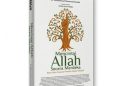“… Sore ini kita berangkat menuju Kebonharjo, bermalam di sana bersama warga. Kabarnya dua hari lagi penggusuran dilangsungkan … dan nanti malam kita persiapkan Panggung Rakyat,” seru Bagja dengan mata merah-melotot dan disapa anggukan seisi forum Perisai Laut. Nampaknya ia belum merebahkan mata semalam suntuk.
Konflik ini kian mendidih antara warga dengan PT KAI. Perusahaan itu sungguh merepotkan sekaligus meresahkan. Mereka menyerobot tanah warga demi meniupkan jiwa pada ribuan batang rel dari Stasiun Tawang ke Pelabuhan Tanjung Mas. Sedangkan warga, garis hidupnya kian tersudut di ujung Laut Utara. Asin nasibnya, hilang rumahnya.
Ketika disaksikan dari atas, siapa pun akan menyangka Kebonharjo adalah anak tiri yang didera seribu cambukan setiap harinya. Suasana kumuh dan penuh lubang jalan bersebelahan dengan Kota Lama di Selatannya yang terus dirias bak anak kesayangan. Mungkin Pemerintah Kota mengidamkan suasana Kota Tua di Jakarta atau Malioboro di Yogyakarta. Dan, “Voila! Semarang punya Kota Lama,” kira-kira begitu ucap Pemerintah Kota yang sok asik.
Tapi hari ini, saat terik mencium ubun-ubun para buruh Jamu Nyonya Meneer, aku mendakwa Bagja melakukan kesalahan: menunjuk aku sebagai penanggungjawab Panggung Rakyat.
“Kau sudah teruji,” tutur Bagja singkat sambil menepuk pundakku dua kali setelah aku mengajukan dalih keberatan atas penunjukkanku. Kemudian ia lenyap seperti tahi di aliran deras.
Rajutan kata itu: sudah teruji, memang khas Bagja. Tapi tetap saja tidak sebanding dengan alasan canggihku kali ini. Seharusnya ia bertanya gerangan apa yang membelokkan garis hidupku. Ah, itu harapan yang sia-sia. Ia tak ‘kan pernah memahami bahwa letupan konflik asmara lebih menderita daripada konflik agraria.
***
“Kar … Karsa!” Aku tidak asing dengan lafal yang memanah gendang telingaku itu. Oh ya, nama—maksudku—aliasku.
Sebenarnya aku agak sebal mendapat alias tersebut. Mereka mengandaikan aku seperti Wilsukarsana. Sosok dari bangsa raksasa yang mampu berubah bentuk apa pun, dan bertugas memata-matai rencana musuh. Ya, mereka tidak keliru, aku memang selalu lolos dari buntutan intel dan taktis di lapangan; tapi toh aku tidak bisa lolos dari jilatan api cemburu kekasihku.
“Sudah ada tiga jaringan yang konfirmasi akan menampilkan teater dan empat orang membacakan puisi malam nanti,” ucap seorang seperti buruh kesiangan.
“Oh, oke. Kabari saja jika ada kendala,” jawabku dengan sedikit mengerling tanpa menoleh. Tapi cangkir kopi di genggamanku tak bisa diam saja, ia memantulkan gelisah tanpa persetujuanku.
“Kau baik-baik saja?” Si Buruh Kesiangan tadi tiba-tiba muncul di hadapanku.
Arunika ….
Bidang wajahnya berkerumun keringat sebiji jagung. Menggelinding dari kening menuju gelombang hidung aquiline-nya. Dan tanpa dosa, keringat laknat itu menjatuhkan diri ke permukaan bibir. Rasanya ingin sekali aku dikutuk menjadi sebiji keringat.
“Sangat baik … hanya ada sedikit masalah,” jawabku rada kikuk.
“Paradoks!” sergah Arunika sembari menggeser kursi di depanku lalu mendudukinya. “Ada masalah? … Jangan sampai jadi pengganjal nanti malam,” Ia menyatukan alisnya.
“Ya. Ada.”
“Nah …” ia menyeringai. Aku ingin memiliki satu seringai seperti itu. “… kenapa tidak kau ceritakan?” tanyanya yang mengandung perintah.
Aih, Arunika! Kau pura-pura tidak tahu atau memang polos? Kau mengimitasi watak Bagja yang tuna-asmara itu. Kau harus tahu bahwa, kau terlibat di dalam konflik asmara antara aku dan Sofiya—kekasihku, juga teman karibmu.
Baiklah, ini mungkin terdengar tiba-tiba. Tapi semua ada awalnya.
Tentu kau masih ingat ketika kita menemui Budi Sekoriyanto*—kuasa hukum warga Kebonharjo—untuk membantu advokasi isu penggusuran, dari mem-blow up ke media hingga mengorganisir massa. Sejak saat itu kita seperti orang penting yang terus menerima pesan dari nomor tanpa nama; sedangkan Sofiya selalu menabung api cemburunya di ujung bibir hingga menggunung.
Pun kini, kita masih tetap hilir-mudik kampus-Kebonharjo untuk menghimpun kabar teraktual. Ya, juga malam ini, Sofiya pasti menganggap Panggung Rakyat adalah acara yang dibuat-buat untuk mempertemukan kita berdua, seperti tuduhannya pada kegiatan-kegiatan Perisai Laut lainnya. Dan aku hampir yakin malam ini akan mencapai titik kulminasi, karena kau kembali ditugaskan bersamaku, lagi.
Aku berwalang hati Sofiya sedang menyelinap di lantai tiga fakultas untuk mengawasi kita berdua, dan mengarahkan moncong snipernya tepat ke jantungku. Semoga saja tidak.
Sebenarnya sudah berulang kali aku mengudar rasa kepada Sofiya bahwa, “Aku dan Arunika tidak ada apa-apa. Kita sering bersama karena berada di satu organisasi, dan kebetulan sama-sama mengadvokasi warga Kebonharjo. Itu saja. Tidak lebih”
Tapi Sofiya selalu menyanggah, “Klise! Seluruh aktivis di berbagai negara sudah meratifikasi alasan itu. Mereka menggunakannya sebagai payung hukum patgulipat.” Memang klise, tapi tidak ada alasan lain yang layak mewakilinya. “Kau hanya mencari pembenaran posisimu, belum menjelaskan perasaan kita. Sama sekali!” tandasnya sebelum menghambur ke kamar kost.
Mengajaknya bergabung Perisai Laut?
Dari strategi marketing sales rokok sampai MLM sudah kupraktekkan, tapi hasilnya nihil. Sofiya jelas lebih memilih bercinta dengan untaian kata Khalil Gibran atau ayun-temayun kalimat Franz Kafka di dalam kamarnya. Bahkan saking putus-asanya, tiga hari lalu aku sempat mencibir, “Seribu kali kau kumandangkan sajak Gibran pun tidak akan mengubah nasib warga Kebonharjo. Lebih baik kau memberi sumbangan nyata!”
“There are those who give little of the much which they have – and they give it for recognition and their hidden desire makes their gifts unwholesome. And there are those who have little and give it all,” ia menangkis dengan muram durja, sebelum akhirnya membanting pintu kamar kostnya.
Aku baru mengetahui di kemudian hari bahwa kalimat itu adalah baris puisi Giving milik Gibran dalam The Prophet.
Akhirnya kusadari, aku dan Sofiya laksana dua archer dari dua kerajaan berbeda yang saling memanah: ia mengabdi pada sastra, sedangkan aku berkhidmat pada gerakan nyata, sekaligus menukas sastra sebagai gerbang negeri antah berantah. Obrolan kami sulit terhubung. Sofiya selalu menghembuskan nafas romantis, sedangkan aku jadi renyem ketika nafas itu meraba daun telingaku.
Kondisinya terbalik seratus delapan puluh derajat ketika aku bersama orang yang saat ini terpendar di bola mataku.
Arunika ….
Ya, kau adalah perempuan yang selalu menghanyutkan ketika bercakap soal agraria. Dari menyebut gagasan Noer Fauzi Rachman sampai Gunawan Wiradi. Atau mengulas gerakan petani Banten, kasus berdarah Mesuji, sampai Henry Saragih—seorang dari rahim petani yang memimpin La Via Campesina. Bahkan kau tidak segan untuk bermalam bersama derita warga Kebonharjo.
Satu ketakjubanku mencuat, ketika pekan lalu kau berhasil menyulut wawasan warga dalam Forum RW, bahwa groundkart yang dibawa PT KAI tidak bisa menjadi bukti kepemilikan tanah. Dan ajaibnya, gelombang optimisme warga muncul kembali setelah sempat redup. Sungguh, kau anggun-bestari. Harus kuakui, aku belum menemukan suaka bergender sepertimu, yang sanggup menampung dunia aktivisme-ku.
Entah sebab apa, kini aku malah tenggelam di lesung pipitmu, dan tidak ingin diselamatkan. Mungkin ada benarnya sangkaan Sofiya: kebersamaan kita memang dibuat-buat. Atau ini semacam post factum? Aku tak tahu pasti. Yang kurasakan kerisauanku lamat-lamat memudar, seiring mengeringnya genangan rob di sepanjang pantura.
***
“Sam … Sam Hardi!” Sayup-sayup suara nun jauh kian mendekat. Ouh, itu nama lahirku! Aku merindukannya. Aku merasa diselamatkan dari dasar palung lamunan yang gulita. Dari manakah asal suara itu?
“Jadi cerita ndak, sih? Dari tadi bengong aja … tapi aku juga tidak maksa.” Ternyata Arunika. Aku hanya mematung dan sekali berkedip. “Baiklah, aku beri kabar baik untuk mengobati masalahmu,” lanjutnya.
Aku menegapkan badan dengan seringai minimalis seperti jongos kerajaan yang menagih upeti.
“Sofiya adalah salah satu pembaca puisi malam ini.” Aku terbelalak.
Ah, apa arti semua ini? Setan apa yang menggoda Sofiya hingga ia mau terjun ke ngarai kesuraman Kebonharjo? Apa pula maksudnya meminta disiapkan dayung dan botol ciu?
“Katanya, dia perlu barang-barang tadi untuk meresapi sajak Dongeng Dukuh milik Pertiwi Hasan,” jelas Arunika sambil menepuk lengan kananku dua kali. Lalu meninggalkan aku yang masih mematung, dan semakin kaku setiap detiknya.
–
*Budi Sekoriyanto telah meninggal, dan pada 2018 namanya diabadikan menjadi nama salah satu gang di Bandarharjo, Semarang.
Yogyakarta, 24 Januari 2021