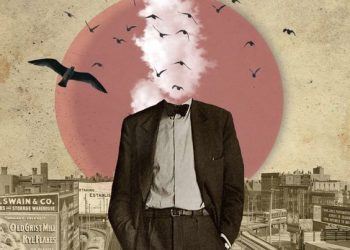Silakan kalau anda ingin memfitnah saya sebagai orang yang sedang misuh atau berkata kasar sejak dari judul. Tapi kontol sebagai kata benda adalah netral. Hanya pikiran kita saja-lah yang menyempitartikannya. Dan persepsi yang peyoratif pun muncul secara sepihak, kemudian ‘nuansa’ yang menyertai kata itu kita selundupkan ke dalam ‘kardus moral’ sesuai selera kita—sehingga terkesan negatif—dan dicap tak bermoral, tak berakhlak. Padahal sebagai kata, kontol cuma kata benda sama halnya dengan pensil dan babi, kuping dan rambut. Apalagi dalam tulisan ini, ia berfungsi sebagai metafor, walaupun memang sarkastik.
Tapi terlepas dari itu, saya ingin bertanya pada pembaca: pernahkah dalam pengalaman singkat hidupmu di kolong langit ini engkau menemui peristiwa bias kontol tersebut? Barangkali di kampus-kampus, teras pos satpam, atau di kantor kecamatan, gedung Dukcapil, sampai di sinetron dan kartun fiksi? Untuk ilustrasi yang lebih gamblang, pernahkah kau mengalami hal-hal menyebalkan semisal bimbingan skripsi yang terasa pilih kasih dan ‘kejam sebelah’ antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan? Jika ingin lebih spesifik, bahkan bisa jadi ada perlakuan favoritism antara mahasiswi cantik dengan mahasiswi biasa aja, sekalipun sama-sama perempuan.
Dalam karya fiksi, agaknya tamsil satire yang sesuai dengan persoalan di atas dapat dijumpai dalam sosok Boa Hancock (karakter Ratu Bajak Laut dalam One Piece karangan Eichiiro Oda). Kata-katanya jitu, “Walaupun aku bertindak seenaknya dan kurang ajar, kalian akan tetap memaafkanku karena aku cantik!” Tegasnya dengan pose khas yang membikin mata para lelaki membentuk emoticon hati—kecuali Luffy tentu saja.
Peristiwa semacam itu membikin saya penasaran. Bahkan sampai menarik garis ke sana kemari dengan multiadegan dan aneka konteks di ranah sosial budaya. Seperti: apakah memang sudah kutukan kaum lelaki untuk mengalami bias semacam itu? Padahal mereka sendiri pelaku sekaligus korbannya, tetapi kenapa sukar sekali untuk mengelak dari lingkaran bias tersebut? Ada dosen cowok, umpamanya, mengistimewakan perlakuannya pada mahasiswi yang goodlooking, sehingga menyakiti perasaan mahasiswa cowok bimbingannya. Namun, kelak siapa tau, begitu menjadi dosen, tidak ada jaminan kalau suatu hari mahasiswa cowok itu tidak mengulangi hal yang sama.
Belum lagi jika menyangkut eksploitasi kecantikan yang beredar nyaris di sektor manapun. Orang (sok) akademik menyebutnya komodifikasi. Dalam bahasa awam disebut jualan. Tidak cuma di dunia industri model, selebriti dan hiburan, eksploitasi kecantikan ini telah juga merambah ke linimasa keagamaan, brosur promosi institusi perguruan tinggi, poster open recruitment NGO dan tim kerja, sampai bahkan pembukaan pendaftaran di pesantren-pesantren. Model yang dipilih pasti yang cantik dan tampan, jarang yang menampilkan orang biasa saja sebagai alat marketing.
Kecantikan perempuan dijadikan objek untuk menarik pelanggan, terutama jika target pasarnya para lelaki. Dan herannya lagi, kaum perempuannya sendiri mau dan tidak sedikit yang bahkan ikut bangga. Kultur eksploitatif dan watak budaya patriarki semacam itu ternyata diterima—bahkan dinikmati—begitu saja, tidak hanya oleh kaum laki-laki, tapi juga bahkan oleh perempuan. Saya jadi pesimistis—berlandaskan pembacaan sosial tadi—dengan upaya para aktivis feminis dan penyetaraan gender, konsep keadilan, dan para penggerak di bidang penumpasan patriarki.
Efek samping dari itu, di antaranya, adalah pola interaksi yang timpang di banyak sektor, mulai dari bidang pendidikan, perusahaan profesional, sampai pesantren sekalipun. Ketimpangan ini turut menyuburkan ketidakmerataan akses terhadap politik, pendidikan, dan domain lainnya. Di samping itu juga, penilaian objektif dalam banyak seleksi atau wawancara akan rawan terkontaminasi oleh bias-bias semacam itu—apalagi jika pelakunya tak sadar dengan adanya ‘kutukan evolusional’ ini.
Yang cantik akan lebih mudah diterima meskipun kurang kompeten, sementara yang tidak cantik akan terdepak dengan sendirinya sekalipun lebih kompeten dan punya potensi besar. Jika hal seperti ini berlanjut terus menerus dan makin dibiarkan, otomatis, secara makro kita tinggal fantadhirus-sa’ah (tunggu kiamatnya). Akan datang kerusakan sistemik karena ditopang oleh SDM yang hanya bagus di wajah, tapi buruk di performa. Silakan tunggu, kalau memang maunya begitu.
Pelestarinya Adalah Mayoritas Kita
Frasa “kutukan evolusional” yang saya rangkai di atas bukan lahir dari ruang kosong. Pertimbangan yang menyertainya saya tumpukan pada beberapa kajian seputar cara kerja otak manusia (neurosains) dan biologi evolusioner. Bahwa sejak dari sono-nya homo sapiens laki-laki sudah mengantongi informasi genetika di DNA mereka secara turun temurun yang mencatat karakteristik perempuan cantik cum seksi dan ini berkaitan dengan aspek kesuburan (fertility). Bahwa yang lekuk pinggulnya begitu, dadanya begini, kaum lelaki suka. Sementara yang tidak begitu, lelaki kurang suka.
Inilah yang menyebabkan adanya kecantikan universal–dan mungkin juga keseksian–yang diam-diam kita sepakati tanpa perlu menggelar konferensi, dan itu sudah terkandung di gen kita. Meski pada sisi yang lain, kecantikan pun memiliki gradasi perbedaan kultural di wilayah masing-masing sebagai hasil pergulatan wacana budaya (seperti konsumsi, industri kosmetik, dan hiburan) di dalam masyarakat. Dari kacamata sains, ini wajar belaka dan pada satu sisi ikut berkontribusi pada kelangsungan hidup dan aktivitas reproduksi homo sapiens sehingga terhindar dari kepunahan. Itu sudah tertanam dalam insting purbawi bedhes sapiens.
Kembali ke bias kontol tadi, barangkali itu dipicu oleh perbedaan partikular yang terkandung dalam otak laki-laki—beserta pelbagai aktivitas neurotransmitter dan hormonalnya. Misalnya kenapa dosen pembimbing pria jauh lebih ‘lunak’ dan baik ketika berurusan dengan mahasiswi cantik, itu ada kaitannya dengan aktivitas otak. Riset tahun 2009 oleh Johan C. Karremans dkk. menyebutkan bahwa lelaki yang berinteraksi dengan perempuan yang atraktif akan mengalami penurunan performa mental.
Kaum pria akan cenderung menuai resiko “pelemahan kognitif” (cognitive impairment) sewaktu berhubungan dengan perempuan yang menurutnya cantik. Setidaknya dari situ kita baru mafhum kenapa ketika meladeni mahasiswi cantik, dosen pria mendadak tumpul daya kritisnya dan kesadisan analitisnya auto-tiarap. Dan hal ini berlaku nyaris ke semua lelaki heteroseksual.
Meski demikian, tentu saja hal itu jangan sampai dijadikan dalih dan stempel legitimasi untuk justru melestarikan budaya pilih-kasih atau favoritism di ruang-ruang publik. Apalagi dalam pengamatan saya sendiri, peristiwa tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum pria saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang tidak sedikit malah ikut menikmati priviledge yang mereka dapatkan karena berwajah cantik.
Usai menggibahkan perihal kecantikan, saya jadi teringat alegori karangan Ariel Heryanto berjudul “Cantik” yang mengilustrasikan lanskap sosial budaya kita lewat anekdot dan kritikan makjleb (coba baca sendiri). Sementara bagi saya secara personal, memang, tidak ada yang bilang kalau cantik itu dosa. Tapi jangan juga karena kecantikanmu, engkau lupa menopang hidup dengan kualitas lain, seperti kecerdasan dan kompetensi. Sementara untuk pihak laki-laki, melihat yang cantik memang nikmat—tanpa harus memungkiri dan bersikap munafik—tapi jangan sampai kenikmatan itu melenakanmu sehingga berlaku tidak adil. Masak rasionalitasmu kalah sama kontol?[]