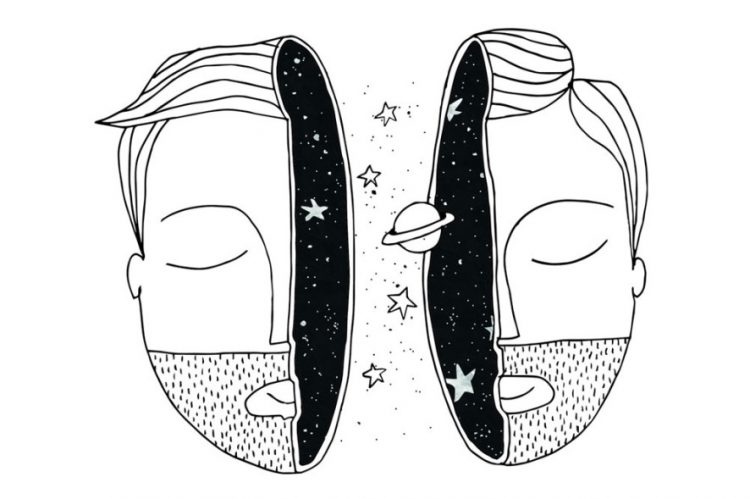Kali ini, hampir sebungkus rokok kuhabiskan sendiri. Mulutku sangat berahi untuk terus menghisap batang demi batang rokok itu. Cangkir kopi di hadapanku juga mulai tak lagi tersentuh oleh jemariku, sebab airnya telah menjelma air mata, dan ampasnya telah kuteguk habis bersama ingatan-ingatan purba.
“Hei…” Kata Sangkala sembari memecah kesunyi-senyapan yang menusuk relung hati, “Sudahkah dirimu bebas?”
“Bebas?” Timpaku heran.
Adakah di dunia ini yang benar-benar bebas? “Bebas itu hanyalah kutukan, Bro….” Iya, manusia itu dikutuk, dinista dan dilaknat untuk menjadi bebas. Kebebasan adalah menjadi Malin Kundang yang menjadi batu. Kebebasan adalah Lembu Suro yang tertimbun di kawah Gunung Kelud. Sekali lagi, kebebasan adalah: mereka yang terlempar dari kebahagiaan.
“Bukankah kebebasan menjanjikan kebahagiaan?”
“Omong kosong!” Sambil kumain-mainkan rokok terakhir di sela-sela jemariku.
Tak ada kebebasan. Kebebasan adalah alibi dari para pendahulu agar mereka terlihat menjadi seorang yang berhasil menaklukkan hidup. Faktanya? Seumur hidup mereka hanya berisi pencarian dan perjuangan yang tak pernah selesai hingga nyawa tak mau lagi dikandung badan.
“Ceritakan padaku, mereka yang mengenakan jubah kebebasan di balik kemeja penderitaan…”
“Baiklah. Maukah kamu mendengarkan kisah mereka yang kini sedang mengenakan jubah kebebasan?” Kusulut lagi sebatang rokok yang baru saja kubeli.
“Muntahkan saja, Bro..” Ujar Sangkala, “Buat aku orgasme dengan kisah mereka yang bebas.”
***
Banyak yang belum menyadari, bahwa kekalahan adalah fondasi pertama dari sebuah kebebasan. Entah kalah dalam percintaan, kalah jabatan, kalah dalam keluarga, dan kalah-kalah lain, yang tentunya membuat banyak insan berlomba-lomba memburu makhluk yang bernama kebebasan.
“Tentu kau ingat, bukan? Tadi sempat kukatakan, bahwa kebebasan adalah sesuatu yang terkutuk, ternista dan terlaknat.”
“Oh… Tentu. Serupa dengan kata Mbah Sartre itu kan?” Sangkala menimpali pertanyaan dengan pertanyaan pula.
Ya, telah kau temu rimbanya. Kebebasan tak dapat didefinisikan. Sebab, mendefinisikan kebebasan sama saja mendefinisikan jutaan manusia yang ada di bumi. Kebebasan adalah manusia itu sendiri, dan manusia merupakan kebebasan itu sendiri.
Sejatinya manusia-manusia ini adalah pejuang-pejuang yang menomorduakan kemenangan. Hidup adalah perjuangan dan keberanian, urusan kalah-menang lain lagi, ungkap Pak Soesilo Toer. Hidup kita hanya mencari dan terus bertanya. Jawabannya? Mati! Hanya mati yang mampu memberikan jawaban; makna kebebasan juga turut terbesit di dalam jasad yang terbujur kaku. Tertawa bersama senyap.
Mari kita mulai perayaan “nihilnya kebebasan” ini dengan tamsil-tamsil terdekat dengan diriku.
Aku memiliki seorang teman, yang selalu tertawa dan nampak bahagia, tapi tidak dengan kedua matanya; sorot yang menyinarkan kekalahan; sorot yang membuka dendam kelam; sorot penuh pencarian. Di balik tawanya, menyimpan tangis dari sebuah ketragisan.
Dia adalah seorang wanita yang periang di luar dan menyimpan dendam kelam dalam memoar. Banyak orang yang telah memberi stigma terhadapnya. Kenapa? Karena hidupnya kini bergelimang kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Bebas yang bagi awam dinilai sebuah kenakalan: merokok, keluar malam, nongkrong, minum alkohol.
Baginya, hal semacam itu adalah perayaan kebebasan yang ia ciptakan menurut versinya sendiri. Tapi, benarkah ia benar-benar bebas? Tidak. Sekali lagi, itu hanyalah pelarian dari kekalahan yang selalu mengejarnya. Kekalahan melawan kejahatan di luar dirinya, dan kekalahan melawan traumanya.
Mirip seloroh Muhidin M. Dahlan dalam bukunya “Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur,” bahwa “Dosa yang dikhidmati akan membawa kita menjadi dewasa.” Begitulah yang dirasakan oleh temanku, Sangkala. Dia menikmati dan mengkhidmati setiap dosanya, karena dengan begitu ia menyelami kedewasaan hidup, yang kadang banal dan beringas.
“Adakah selain itu?” Sangkala kembali memecah kepiluan sore itu.
“Ada…. Banyak, bahkan. Tapi musykil untuk kutumpahkan semua di sini. Ceita kawanku itu pun tak sepenuhnya kugambarkan. Lebih kelam dan memilukan sebenarnya. Biar waktu saja yang membacanya kelak.”
Tempo hari, ada juga seorang kawan yang begitu lampau dalam menyelami dunia kepenulisan. Karya-karyanya menyaingi jumlah umurnya yang hampir memasuki kepala tiga. Saat kutanya, mengapa ia terus menulis dan berkarya? Jawabannya begitu singkat, padat, dan berbobot: “Aku gagal.”
Ia berangkat dari kegagalan. Dengan kegagalan sebagai hulu, kata-kata dijadikannya sampan untuk sampai ke hilir. Dia mengungkap kegagalannya dalam merumuskan cinta sebagai sebuah kekalahan yang paling paripurna. Kawanku telah dikalahkan oleh cinta dan seseorang yang berjanji untuk memberikan makna-makna cinta itu sendiri.
Lewat tulisan-tulisannya, aku dapat menerka bahwa dia sedang berjalan menapaki rimba kegelisahan dalam hidup. Lewat tulisannya−yang jarang dipublikasikan−dia berhasi mengekspresikan kebebasannya dalam hidup. Bebas yang kalah. Saat kutanya, apakah ia masih memiliki harapan? Lagi dan lagi, aku ditampar oleh jawabannya yang lugas sekaligus miris.
“Harapanku masih tersisa dalam saku kemejaku yang lusuh oleh keegoisan. Hanya sebesar saku!”
Apa artinya? Memang begitu seharusnya hidup. Simpanlah harapan dalam saku kemejamu. Kelak pada saat yang tepat dan waktu yang perlu, harapan itu akan keluar secara tiba-tiba tanpa perlu aba-aba. Sebab, hidup yang penuh harapan adalah hidup yang selalu dirundung oleh kegelisahan. Gelisah akan esok hari, gelisah akan harapannya, gelisah akan kegagalannya. Lantas, kapan kau dapat menikmati hidup, yang begini-begini saja?
***
Sebenarnya masih banyak lagi orang yang pernah kutemui dengan puspawarna kekalahan dan kebebasan. Jika ingin tahu semua, datangilah lorong-lorong gelap kehidupan; dosa-dosa sunyi di prostitusi; ruang-ruang senyap dalam dirimu.
Di tempat-tempat seperti itu, kebebasan adalah barang obralan yang dijual secara murah dan dikapitalisasi dalam skala besar-besaran. Kebebasan-kebebasan itu lahir dari rahim kegelisahan, kegagalan, dan kekalahan.
Kekalahan itulah yang mengutuk manusia menjadi bebas. Bebas yang tak berbatas. Buas.
“Apakah kebebasan sebanal itu?” Sangkala mulai letih dan bosan.
“Ya, bebas bisa banal dan janggal.” Sambungku, “Bebas bisa juga mengarahkan kita pada keabadian yang sejati: mati.”
Kebebasan mana lagi yang kau cari? Cukup sudah. Orang-orang di luar sana memperingati kekalahan dan kegagalannya dengan kebebasan. Jika hendak bebas, maka taklukkanlah kekalahan. Jika ingin kalah, maka ciptakanlah dirimu se-dirimu mungkin. Jangan biarkan hegemoni dan intervensi selain dirimu memaksakan kehendakmu.
“Baiklah, Sangkala. Aku hendak pulang ke palung yang paling purba: kesepian.”
“Pulanglah…. Kuberikan diriku seutuhnya untuk kesepianmu,” Sangkala menyatukan tubuhnya dengan diriku, selama-lamanya. Sekalah-kalahnya.
Yogyakarta, 26 Oktober 2020