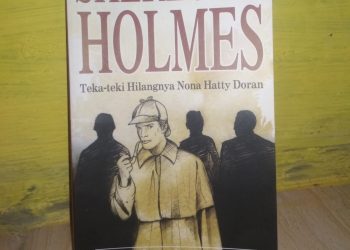Kurang lebih tiga bulan lagi umat Islam merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2021 atau 1442 Hijriah ini. Sebuah puisi yang menarik perhatian banyak orang terkait dengan peristiwa atau momen ini adalah puisi karya Sitor Situmorang berjudul “Malam Lebaran”.
Banyak pembaca puisi yang sulit memahami makna dan pesan yang terkandung di dalam puisi “Malam Lebaran” karya Sitor Situmorang ini. Termasuk saya. Ini puisi terpendek karyanya yang pernah dimuat di majalah Zenith dan terkumpul dalam buku Dalam Sajak (1955). Banyak orang memujinya. Namun, banyak pula orang yang mencemoohnya.
MALAM LEBARAN
bulan di atas kuburan
Banyak tafsir yang ditulis oleh pembaca mengenai isi, makna, atau pesan puisi tersebut. Mereka mendasarkannya atas teks puisi tersebut semata. Entah dengan pendekatan struktural ataupun semiotik.
Semula saya pun demikian. Hanya membaca kata per kata kemudian menafsirkannya begitu saja. Dalam benak bertanya: Mana mungkin pada tanggal 1 Syawal tepat “malam lebaran” terlihat bulan mengambang di langit yang menaungi kuburan? Sesuatu yang musykil. Tak masuk akal.
Penanda 1 Syawal adalah hilal, bulan sabit “njlirit” nan kecil yang terlihat hanya sangat sebentar. Tetapi, di dalam puisi Sitor Situmorang tersebut digambarkan “bulan” yang meski tidak purnama, terlihat oleh mata telanjang. Nonsens, itu logikanya!
Jika puisi tersebut kita anggap menggunakan metafora dan bersifat simbolik, maknanya menyiratkan aura positif. Begini kurang lebih. Ketika umat islam di seantera bumi merayakan malam Lebaran (lebih tepat dikatakan malam takbiran karena esok paginya umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri), kebahagiaan dan kesejahteraan itu datang bersamanya.
Latar Belakang
Rupanya kita melupakan latar belakang proses penciptaan puisi tersebut. Itu sebabnya, banyak interpretasi terhadap puisi tersebut meskipun itu sah-sah saja. Bukankah pembaca memiliki kebebasan dalam menemukan dan memberikan makna atas puisi yang telah dibacanya?
Inilah latar belakang proses penciptaan puisi “Malam Lebaran”, yang merupakan pengakuan Sitor Situmorang, saya kutip dari buku Proses Kreatif: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang II (Editor Pamusuk Eneste, Jakarta: Gramedia, 1984, halaman 1-2).
“Tahun 1954, Jakarta. Beberapa hari sesudah Hari Raya Idlfitri umat Islam.
Suatu sore saya berniat pergi bertamu ke rumah Pramoedya Ananta Toer, untuk kunjungan hala lbihalal. Apa lacur, rumah (gubuk)-nya di daerah Kober sepi orang dan hari sudah malam ketika saya sampai. Kecewa amat rasanya!
Pulang dari daerah perkampungan tempat tinggalnya, yang berselokan-selokan mampet yang bau busuk, saya kesasar ke suatu tempat yang penuh pohon-pohon tua dan rimbun, serta dikelilingi tembok. Ada bulan. Karena kepingin tahu ada apa di balik tembok yang seperti tembok loji di Jawa itu, saya mendekatinya. Berdiri berjingkat, di atas seonggok batu, saya berhasil melongok mencari tahu ada apa di balik tembok itu: ternyata pekuburan berisi berbagai ragam bentuk kuburan berwarna putih, tertimpa sinar bulan di sela-sela bayangan dedaunan pepohonan! Pekuburan tua orang Eropa penuh tanda salib!
Saya terpesona, sejenak saja, mungkin hanya beberapa detik, mengamati tamasya itu! Bahkan terpukau seperti tersihir. Saya lalu berpaling, turun dari onggokan batu. Rasa kecewa ini diharu biru oleh kesan bulan di atas kuburan (rekaman ingatan dalam kata-kata).
Kesan yang terumus dalam kata-kata secara spontan itu, terucap dalam hati berulang-ulang, terus-menerus memburu ingatan, kemudian melemah, tapi tidak lenyap sama sekali, di saat saya mendekati jalan raya, yang penuh keriuhan lalu lintas.
Saya merasa terasa terasing dari bunyi kesibukan, walaupun jelas tetap mampu bergerak melakukan apa yag harus dilakukan: mencegat oplet tumpangan pulang.
Pulang? Tujuan rutin, ke rumah sendiri, terasa hilang arti. Bulan itu, kuburan itu. Kematian, sedang di atas dan di sekelilingnya: dunia, ya, jagad yang berjalan dan beredar terus, di hari baik, di bulan baik orang percaya!”
Puisi Instan
Jadi, masuk akallah jika bulan tampak mengambang di langit di atas kuburan. Sebab, seminggu setelah 1 Syawal (Idul Fitri) bulan tampak setengah purnama, belum purnama penuh. Bulan yang tampak itu rupanya dikaitkan oleh penyairnya dengan situasi Idul Fitri atau Lebaran yang masih terasa auranya.
Sekali lagi kita baca puisi “Malam Lebaran” karya Sitor Situmorang tersebut.
MALAM LEBARAN
bulan di atas kuburan
Sangat terasa dan jelas bahwa puisi di atas belum mengalami proses pengendapan. Apa yang terekam melalui panca indera, terutama mata, langsung ditumpahkan ke dalam kata-kata; bulan, di, atas, kuburan. Sungguh gamblang bahwa puisi tersebut merupakan puisi instan, bukan puisi sublim.
Puisi tersebut terlihat hanya permainan kata-kata yang sengaja ditulis untuk membuat pembaca, terutama pembaca Muslim, disesaki pertanyaan yang menuntut kelogisan dan keakurasian dalam memilih dan menggunakan diksi di dalam puisi. Keinginan berhalal bilhalal Sitor Situmorang pada malam lebaran dengan sahabatnya yang memeluk agama Islam, memaksanya menulis puisi yang dangkal dan main-main.
Ini sesuai dengan pengakuannya bahwa puisi tersebut lahir karena kesan sesaat atau impresi yang merayu jiwa, hati, dan batinnya. Bisa jadi kesan itu malah menerornya hingga lahirlah puisi yang membuat banyak pembaca tergelincir menafsirkannya.
“Tahun 1954, Jakarta. Beberapa hari sesudah Hari Raya Idul Fitri umat Islam.”
Waktu Sitor Situmorang menulis puisi “Malam Lebaran” adalah beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri saat umat Islam merayakan kemenangannya setelah sebulan penuh berpuasa. Frasa beberapa hari bisa bermakna dua-tiga hari atau bahkan seminggu.
Pulang dari daerah perkampungan tempat tinggalnya, yang berselokan-selokan mampet yang bau busuk, saya kesasar ke suatu tempat yang penuh pohon-pohon tua dan rimbun, serta dikelilingi tembok. Ada bulan
….
Kesan yang terumus dalam kata-kata secara spontan itu, terucap dalam hati berulang-ulang, terus-menerus memburu ingatan, kemudian melemah, tapi tidak lenyap sama sekali, di saat saya mendekati jalan raya, yang penuh keriuhan lalu lintas.
Selain itu, puisi “Malam Lebaran” ciptaan Sitor Situmorang tersebut dapat saya modifikasi dengan menggunakan tipografi seperti ini tanpa mengubah makna atau pesannya.
bulan
di atas
kuburan
Bandingkan dengan puisi berikut.
Tuhan, kami sangat sibuk. (“Keluhan”, K.H. A. Mustofa Bisri)
Meski cuma satu larik, puisi “Keluhan” karya K.H.A. Mustofa Bisri di atas terlihat melalui proses pengendapan. Ini sebuah puisi yang ditulis melalui proses perenungan dan penghayatan yang dalam. Betapa manusia itu sangat egois sehingga ia merasa sangat sibuk dalam mengurus dan mengelola kehidupannya di dunia ini.
Tak ada waktu sekejap pun untuk Tuhan, untuk berdoa memohon apa pun kepada-Nya. Ini sebuah puisi yang menggambarkan keangkuhan atau kesombongan manusia. Puisi yang meledek dan mengkritik manusia yang sangat beranfsu memburu nikmat dunia sehingga karena kesibukannya manusia mengeluhkannya kepada-Nya.
Puisi “Keluhan” karya K.H.A. Mustofa Bisri jika saya ubah tipografinya, tampak seperti berikut ini.
Tuhan,
kami
sangat sibuk.
Meskipun maknanya tak juga berubah, greget dan semangat mengeluh yang diungkapkan oleh penyair sangat terlihat ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Menerima Keluhan. Tipografi vertikal juga menggambarkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan
Jadi jelaslah bagi kita bahwa puisi “Malam Lebaran” karya Sitor Situmorang ini merupakan puisi instan yang ditulis spontan, tanpa pengendapan, dan hanya sesaat menarik perhatian orang. Kontradiksi judul dengan larik puisi, menandakan bahwa puisi tersebut tidak bisa diterima oleh akal sehat. Padahal, karya sastra, termasuk puisi tentunya, juga ditulis dengan bertolak dari kenyataan hidup ini, namun tetaplah dalam koridor logika yang wajar.
Meskipun saya percaya bahwa tidak ada puisi yang hampa makna atau nihil arti, puisi “Malam Lebaran” bukanlah contoh puisi yang baik. Kesan yang menyelinap di hati adalah bahwa puisi ini merupakan puisi impresi yang sekadar memanfaatkan momentum perjumpaan secara indrawi tanpa perenungan yang sungguh-sungguh. Demikianlah.
Cibinong, Februari 2021