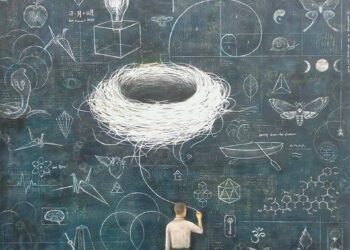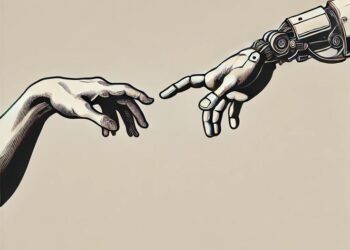Eksistensi Jalur Rempah Nusantara
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, dialektika pembahasan jalur rempah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Dimulai dari pameran di Museum Nasional di Jakarta (18-25 Oktober 2015) dengan tajuk “Jalur Rempah: The Untold Story”, merambah pada kegiatan “Ekspedisi Jalur Rempah 2018: Sejarah Jalur Rempah dan Kekayaan Hayati Kie Raha” oleh Kemendikbud (28 September-10 Oktober 2018); hingga pelaksanaan Muhibah Budaya Jalur Rempah oleh Kemendikbud-Ristek yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus-28 Oktober 2021 silam. Kegiatan tersebut menunjukkan bukti adanya semangat penelusuran perjalanan rempah yang menjadi bagian dari sejarah panjang dan memori kolektif masyarakat Indonesia (Rahman, 2019; 348).
Konsistensi pembahasan jalur rempah sebagai isu akademis menyajikan logika penalaran yang utuh tentang pentingnya pengetahuan terkait ekonomi rempah dan jalur niaga masa lampau (Ririmasse, 2017; 49). Jalur rempah adalah istilah untuk jaringan niaga yang menghubungkan belahan barat dan timur dunia. Jalur ini membentang dari pantai barat Kepulauan Jepang, melintasi Kepuluan Indonesia, melewati India hingga daratan Timur Tengah dan berlanjut ke kawasan Mediterania menuju Eropa. Jalur ini memiliki jarak bentang sekitar 15.000 km (en.unesco).
Diskusi akademis yang kerap muncul ketika membahas tentang jalur rempah adalah gagasan bahwa tumbuh kembangnya jaringan niaga di Nusantara memiliki simpul yang lururs dengan kedatanga para mufasir dari Asia Barat, penjelajah Tiongkok dan pengelana dari Eropa (Ririmasse, 2017; 47). Terletak pada titik persilangan yang strategis, Nusantara, selain dijadikan sebagai daerah transit bagi komoditi dari wilayah timur dan barat, juga merupakan daerah berkumpulnya para pedagang mancanegara (Syafiera, 2016; 722).
Sejak awal, beberapa tempat di Nusantara dikenal sebagai kawasan penghasil komoditi rempah langka. Sumatra dan Jawa menjadi rumah bagi produk kapur barus dan lada. Kepulauan Nusa Tenggara menjadi pulau-pulau penghasil kayu harum cendana. Wilayah Aru menjadi tempat komoditi langka mutiara dan bulu burung cendrawasi. Serta primadona rempah-rempah abad 16-18 M, Ternate dan Tidore menjadi habitat paling ramah untuk cengkeh dan pala (Ririmasse, 2017; 49).

Untuk menghubungkan jalur niaga Nusantara, pelabuhan Malaka tampil sebagai aktor utama lalu-lintas perdagangan dan pelayaran abad ke-15 M. Pada akhir abad itu, ratusan pedagang dari Arab, Persia, India, dan China berbodong menuju Malaka untuk melakukan aktivitas perdagangan. Hal ini memicu geliat di antara orang Eropa. Hingga akhirnya pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis (Syafiera, 2016; 722). Kejatuhan pelabuhan niaga ini mengakibatkan lahirnya pelabuhan-pelabuhan baru yang mengambil peran penting sebagai penghubung niaga di Nusantara. Salah satunya yaitu pelabuhan Makassar. Sebagai rumah bagi kapal-kapal intornasional, kota maritim ini menjadi titik tolak niaga rempah di Indonesia bagian timur.
Makassar dalam Arus Niaga Internasional Abad ke-17 sampai Abad ke-20
Pada awal abad ke-16, perdagangan di Nusantara lebih terfokus pada wilayah bagian barat dengan pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan rempah. Interaksi perdagangan yang terjadi di wilayah Sulawesi hanya sebatas perdagangan barang dagang hasil sendiri seperti hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan (Syafiera, 2016; 729). Baru sekitar pertangahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Sulawesi mulai melibatkan diri dalam perdagangan rempah skala global terutama setelah jatuhnya Malaka di tangan Portugis pada 1511. Salah satu pelabuhan yang ramai dikunjungi di daerah Sulawesi yaitu pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan.
Makassar, dalam arus perkembangan perdagangan abad ke-17, perlahan menapaki posisi sebagai kota pelabuhan Internasional dan menjadi pusat perdagangan untuk wilayah Indonesia bagian timur (Nur, Dkk., 2016; 617). Pada paroh pertama abad-17, Makassar dianggap sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur dan menjadi titik temu antar dunia niaga bagian timur (Maluku dan Irina Jaya), barat (Kalimantan, Malaka, Sumatera, Jawa, Asia Selatan dan Eropa), utara (Philipina, Jepang dan China) dan selatan (Nusa Tenggara dan Australia) (Nur, Dkk., 2016; 617).
Pada kurun waktu itu pula, Makassar berhasil memegang supremasi perdagangan sesudah Jawa Timur dan berperan sebagai tempat berkumpul barang-barang dagang terutama rempah-rempah dari Maluku yang kemudian dikirim ke barat melalui pedagang-pedangan melayu yang berpusat di Malaka (Rasjid & Gunawan, 2000; 52).

Komoditi utama dari perdagangan di Makassar adalah rempah-rempah, beras, jagung, kopi, kopra, kain tenun dan budak, serta kayu cendana dari Timor dan Solor (Nur, Dkk., 2016; 617). Perdagangan dikuasai sepenuhnya oleh raja dan kaum bangsawan dari Kerajaan Gowa (Makassar). Aktivitas perdagangan itulah yang menjadi faktor utama bagi Raja Gowa dalam mengadakan ekspansi sampai ke Buton, Selayar, Seram, Buru, Timor, Bima dan Flores dengan tujuan agar daerah taklukkan itu bisa dimonopoli barang dagangannya. Dengan cara itu, bandar Sombaopu di Makassar dapat melayani permintaan para saudagar asing, sehingga pelabuhan Makassar akan berkembang dengan semakin banyaknya para pedagang dan kapal-kapal yang berlabuh pada pelabuhan itu (Nur, Dkk., 2016; 618).
Kemajuan Makassar dan bandar Sombaopu dalam bidang perdagangan ini menarik perhatian para tetinggi Verenigde Oost-Indische Compagni (VOC) yang berlangsung hingga Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasainya. Langkah pertama yang mereka ambil adalah melarang pedagang Bugis-Makassar untuk berdagang di Maluku. Namun, perintah ini tidak dilaksanakan.
Hingga akhirnya pada abad ke-19 dan 20, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melakukan penaklukkan. Dimulai dengan Kerajaan Bone yang berhasil ditaklukkan, menyusul kerajaan-kerajaan lainnya termasuk Kerajaan Gowa. Sejak tanggal 30 Juli 1905, Pemerintah Hindia Belanda berhasil menguasai Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Setelah kekalahan kerajaan Gowa, Belanda kemudian mengambil alih perdagangan. Penaklukkan Kerajaan Gowa juga mengakibatkan terjadinya pengusiran besar-besaran keluar dari Makassar.
_________________________________
Sumber Bacaan:
http://en.unesco.org/silkroad/
Nur, Nahdia, dkk. “Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan pada Tahun 1900-an Sampai Dengan 1930-an”. Jurnal Ilmu Budaya. Vol. 4. No. 1. Juni 2016. Halaman 617-712.
Rahman, Fadly. “Negeri Rempah-Rempah: dari Masa Bersemi hingga Gugurnya Kejayaan Rempah-Rempah”. Jurnal Patanjala. Vol. 11. No. 3. September 2019. Halaman 347-362.
Rasjid, Abdul & Gunawan, Restu. 2000. Makassar sebagai Kota Maritim. Jakarta: CV. Putra Prima.
Ririmasse, Marlon NR. “Sebelum Jalur Rempah: Awal interaksi Niaga Lintas Batas di Maluku dalam Perspektif Arkeologi”. Jurnal Kapata Arkeologi. Vol. 13. No. 1. Juli 2017. Halaman 47-554.
Syafiera, Aisyah. “Perdagangan di Nusantara Abad ke-16”. Antara: e-Journal Pendidikan Sejarah. Vol. 4. No. 3. Oktober 2016. Halaman 721-735.