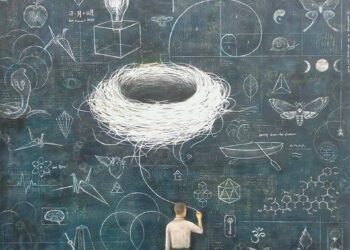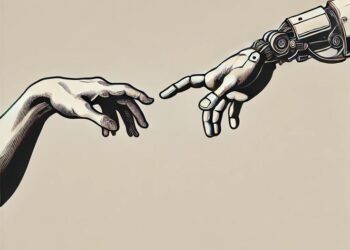Fenomena “musiman” seringkali terjadi secara alamiah, meskipun tak lepas dari dorongan segala keadaan dan kenyataan yang singgah menerpa hidup kita. Ia bagaikan angin sepoi-sepoi, yang lalu tersebar, bergerak ke sana kemari, menyelinap ke dalam “lakuan” suatu masyarakat. Merasuki tingkah laku setiap orang pada batas setiap kehendak dan nafsu. Ia antara sekadar menghibur, melenakan, menganjurkan, dan pada saat yang sama, juga menitipkan pesan, tanda, dan makna secara terselebung.
“Musiman” seperti ajakan untuk kita ke sana, lalu membiarkan sesuatu yang tak pasti itu datang. Penerimaan biar menjadi salah satu bentuk konsekuensi, tidak bisa tidak, maka kita biarkan sesuatu yang tak pasti itu datang untuk kita.
Kenyataannya kemudian kita tidak mewaspadai, mengolah, melainkan hanya menuruti apa maunya nafsu. Terlanjur acuh tak acuh pada beragam kemungkinan, kehendak orang banyak dan kehendak pribadi. Hal ini menandai bahwa titik-titik kelemahan kita, ialah tidak bisa mengelola kehendak orang banyak ke dalam kehendak pribadi. Diam-diam kita idak mampu mengendalikan kehendak pribadi yang membebek. Bahkan kita tidak sedia menggali anugerah Allah berupa apa sebetulnya potensi pemberian-Nya untuk kita.
Pendek kata, fenomena musiman ialah kesementaraan yang akan senantiasa berlalu. Kadang teramat cepat, kadang perlahan-lahan. Sedangkan kalau menurut kehendak pribadi, waktu tidak akan pernah cukup. Persoalannya adalah bagaimana kita akan mengurai musiman tentang kemauan untuk sekadar hiburan, nafsu bagi pelampiasan, pergulatan antara kehendak orang banyak dengan kehendak pribadi. Yang menjadi krusial kali ini adalah menggali kepekaan terhadap “kultur musiman” pada diri kita sendiri.
Tetapi, secara kegembiraan, musiman itu merupakan bahan lelucon yang mencerminkan prinsip bahwa keindahan, bukanlah bingkisan sembako pemerintah, melainkan sesuatu yang mesti kita hayati dalam diri. Jadi, kata Mohamad Sobary, ia melambangkan resistensi: pembangkangan sipil dan aneka corak penolakan terhadap pemerkosaan kodrat kemanusiaan.
Belum usai pemandangan “manusia silver” sebagai pantomim jalanan, kini mulai keluar “manusia badut” sebagai hiburan yang mengandung kritikan secara non-verbal. Tentulah kalau kita selami keduanya bergelimang makna. Terutama sekali soal bertahan hidup di tengah pandemi, betapa kenikmatan hidup ialah bekerja. Pokoknya ubet terus, maka biarkanlah rezeki itu datang kemudian.
Demikian artinya, kegiatan tersebut berjalan tanpa tendensi. Semacam suatu kritik terhadap kinerja pemerintah yang lamban dalam menangani situasi pandemi, meskipun maksudnya dan gambaran kritiknya sangat mudah untuk kita tangkap ke arah sana.
Tiap kali memandang “manusia silver” bergaya masing-masing, ketidakpahaman membuat kita bertanya-tanya sendiri apa maksudnya ini. Apakah pemerintah sanggup mengerti keadaan rakyatnya ataukah kita sebagai rakyat biasa memang selalu diajarkan untuk tidak dan jangan sampai paham pada apa yang dilakukan pemerintah. Kekacauan komunikasi antara wakil-wakil pemerintahan dengan rakyatnya seringkali melahirkan kegagapan putusan.
Dan dalam hal ini, pemerintah cenderung menjadi sesuatu yang asing. Tak terpahami. Nyaris serba tak menentu. Makanya “silver” mungkin berarti tidak jelas apakah pemerintah harus menolong dirinya sendiri terlebih dahulu ataukah mendahulukan kepentingan orang banyak.
Saat itulah kehadiran “manusia badut” yang tak terencana itu, justru menimbulkan efek kegembiraan yang bukan berasal dari melucu. Senyum di topengnya menyempurnakan penderitaan masing-masing yang mungkin saja hampir selalu kita tertawakan dalam hati. Ia mungkin menjadi bahan lelucon tentang suatu negara yang berkembang untuk tidak tahu dan tidak ambil pusing akan perkembangan rakyatnya. Belum jika menyoal kerusakan alam dan lingkungan hidup. Hadeuh, tapi lagi-lagi, dalam kondisi semenderita apapun rakyat Indonesia, ternyata masih bisa tersenyum dan tertawa meluapkan rasa syukur.
***
Kita pun mengalami pelbagai aktivitas “musiman” mulai dari bersepeda, ikan cupang, dan kini giat bulu tangkis. Tiap orang yang tidak tahu seketika mendadak merasa tahu banyak hal tentang sepeda, ikan cupang, dan bulu tangkis. Seolah merasa paling mengerti, tetapi tidak pernah menempuh jalan sungguh-sungguh belajar dan mendalaminya. Betapa arus yang kuat membawa kita seringkali menyertai kebosanan dan kejenuhan tingkat tinggi. Kehendak “musiman” lebih sekadar pemuasan nafsu–di samping pelengkap hiburan.
“Kultur Musiman” bagaikan sesuatu yang tiada habisnya. Tiada hentinya. Timbul-tenggelam dan akan selalu berulang. Mari kilas balik sejenak: sesudah “Sunda Empire” tenggelam, “Keraton Agung Sejagat” tumbang, lalu kini muncul “Kerajaan Angling Darma”. Dalam pandangan tentang kenegaraan, apakah ini akan berarti mengancam keberadaan suatu negara, atau katakanlah, mengusik ketentraman suatu negara?
Yang jelas secara umum, tanpa tedeng aling-aling, hal tersebut selalu dianggap sebagai suatu kekonyolan yang pantas untuk dicemooh dan ditertawakan. Akibatnya, berdampak pula pada pengetahuan kita terhadap sejarah kerajaan di Nusantara kian menjadi dipersempit hanya sebatas itu. Sementara kita semua belum menemukan apa-apa. Minimal pesan, tanda, dan maknanya yang barangkali berfaedah bagi implikasi etik laku keseharian. Terus bagaimana jika sesuatu “musiman” mampu bertahan sekaligus berkepanjangan dalam memengaruhi ekosistem proses kreativitas?
“Di Pamulang,” kata seorang kawan, “hampir setiap hari saya menyaksikan muda-mudi sastra hanya sibuk menikmati hasil kreatif era sebelumnya, tanpa pernah mengalami sendiri betapa galau dan nikmatnya proses penciptaan. Mereka seperti ‘orang-orang tunasastra’ yang minta pedoman untuk berbuat dan harus melakukan apa?”
“Sepengalaman saya bersaksi, kala itu kegandrungan kita pada kemungkinan merupakan sentrum spontanitas, sambil mengerahkan daya naluri dan memicu insting terhadap keindahan. Sementara, saat ini, cobalah diamati kembali, situasinya amat bergantung pada adanya dorongan dan motivasi dari luar diri (eksternal). Tetapi bukan berarti maksud saya membandingkan satu sama lain, melainkan mungkin keadaan seperti itu juga merupakan efek dari ketergantungan “musiman” yang menyebar ke mana-mana.”
“Mengapa iklimnya sangat jauh berbeda dengan saat kita giat berproses kreatif dan latihan teater dahulu?”
“Cobalah pakai pengamatanmu sendiri untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Bukankah kita berproses dalam ikatan kebersamaan yang kuat, kesediaan untuk berbagi, bertindak dan berlaku sebagaimana kita belajar menjadi manusia. Yang indah dan wajar. Seluruh kehendak kita tidak datang dari kawan atau lawan, melainkan sebuah penerimaan dari Allah yang tak jemu-jemu kita menyongsongnya.”
“Dan waktu itu, tidak ada seorang pun yang menyuruh kita agar melakukan ini-itu, seluruhnya berkat kepekaan dan penghayatan masing-masing dalam merumuskan keadaan sekitarnya, sehingga secara alamiah seakan-akan kita menghadirkan suatu tanggapan kreatif dan mengalirkan tawaran permintaan atas kondisi lingkungan tempat kita berproses.”
Selanjutnya dalam tiap percakapan di atas, bab kreativitas di Pamulang menyembulkan pesan kerinduan, selain tantangan yang menagih untuk kita berproses bersama lagi. Bahkan, pertanyaan kawan saya tadi baru bisa dipahami hanya jika telah kita temukan sepasang kata ajaib: kebersamaan dan kegembiraan. Jejaknya seperti lenyap ditelan “kultur musiman”. Langkah-langkah proses kreatif di Pamulang, riwayatmu kini akan ke manakah?[]