28 Maret 2024 Masehi. Malam 18 Ramadhan 1445 Hijriah. Saya tiba di Ladaya, Tenggarong, setelah menempuh lebih dari satu setengah jam perjalanan dari Samarinda–membawa diri yang tak bersih.
Pikiran saya dipenuhi asumsi-asumsi dan imajinasi-imajinasi tentang apa yang bakal saya dapatkan di acara Sahur Mayur ke-12. Ini sebuah acara rutin tahunan yang diselenggarakan Lanjong Foundation. Tentu saja pada bulan Ramadhan. Isinya berbagai macam pertunjukan, diakhiri sahur bersama. Munculnya asumsi dan imajinasi tersebut, terutama, dipicu oleh tema besar acara yang mereka angkat: Para Pencari Panggung.
Mengeja Konteks
Frasa Para Pencari Panggung segera menarik ingatan saya kepada sinetron relijius populer ‘spesialis’ bulan Ramadhan: Para Pencari Tuhan. Jika sinetron yang dibintangi oleh Dedy Mizwar itu berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah kampung Jakarta yang bertungkus lumus dengan segala dinamika dan kejenakaannya mencari Tuhan, perjalanan orang-orang yang tersesat demi menemukan Tuhan, lantas apa yang akan saya temui dalam Para Pencari Panggung?
Konteks situasi sosial politik serta cara kita hidup di masa kini kemudian ikut melengkapi asumsi dan imajinasi saya. Pemilu yang baru saja berakhir masih membawa gema yang bukan lamat, melainkan gaduh. Tentu saja kita semua mafhum bahwasanya periode pemilu adalah masa ketika jalanan dan ruang publik tiba-tiba menjelma galeri raksasa tanpa dinding. Sebuah griya di mana berbagai macam seni visual jelek yang menampilkan sosok-sosok berpose ramah lengkap dengan tulisan-tulisan buruk dipajang.
Baca juga: Esai “Mengapa Perlu Membaca Sastra?”
Kota dan desa, gedung dan lapangan, bahkan rumah pribadi, kemudian salin rupa menjadi panggung teater dengan aktor-aktor para calon legislatif yang berakting buruk dalam lakon-lakon karangan mereka sendiri. Lakon-lakon berisi janji-janji supaya masyarakat (penonton) memilih mereka pada hari pencoblosan.
Singkatnya, masa pemilu adalah masa para pencari panggung.
Namun, sesungguhnya, bukan hanya para politisi itu yang sedang mencari panggung. Kita semua, saya kira, sudah, sedang, dan masih akan mencari panggung sendiri-sendiri. Dan media sosial menyediakan diri untuk agenda kita tersebut.
Ada masa-masa ketika dulu sekali, seorang remaja menulis buku harian dengan malu-malu untuk meluapkan kesedihan, keluh kesah, atau kebahagiaan sederhana karena mendapat senyuman dari orang yang ditaksir, misalnya. Sebuah buku harian yang kita simpan rapat-rapat dalam laci di dalam kamar. Seakan-akan belum cukup, buku harian itu juga kita gembok. Kuncinya kita bawa ke mana-mana dalam dompet. Sebuah laku melindungi rahasia diri kita, identitas kita, kepribadian kita.
Hari ini, orang-orang membongkar buku hariannya dalam media sosial. Orang-orang menulis kesedihan, keluh kesah, kebahagiaan di sana. Laku yang dalam sejumlah aspek mirip, namun menyimpan perbedaan besar. Yakni bahwa apa yang dulu bersifat rahasia–dan perlu disimpan rapat-rapat–kini dibuka selebar-lebarnya agar orang lain tahu.
Kita merasa bahwa setiap orang di dunia yang fana ini mesti tahu apa saja yang kita kerjakan atau rasakan, mulai dari aktivitas makan yang sederhana hingga pernikahan yang sakral. Orang-orang harus tahu, dan dengan begitu, orang-orang akan sadar kita ada. Dan dengan begitu, kita mendapat panggung dan validasi untuk diri kita sendiri.
Kita, orang-orang hari ini yang berkutat di media sosial, adalah para pencari panggung.
Asumsi-asumsi seperti itulah yang selanjutnya membentuk imajinasi-imajinasi dalam batok kepala saya tentang apa yang mungkin bakal saya temui di ampiteater Ladaya: baliho besar caleg dibentangkan di atas panggung, sejumlah orang menyembah baliho tersebut, sebagian mengencinginya; dialog-dialog tidak nyambung yang disusun dari komentar-komentar di media sosial; video-video unggahan sampah atau meme-meme yang direspon sedemikian rupa.
***
Baca juga: Novelet Nirmakna & Pandemicthink
Asumsi-asumsi dan imajinasi-imajinasi adalah asumsi-asumsi dan imajinasi-imajinasi dan akan tetap menjadi asumsi-asumsi dan imajinasi-imajinasi. Teater sebelum teater yang berlangsung dalam kepala saya akan tetap menjadi teater sebelum teater yang tak pernah benar-benar terwujud.
Di ampiteater Ladaya, sekira setengah jam sebelum tanggal berganti ke 29 Maret 2024, Teater Bastra memindahkan Makkah pada abad ke-7 Masehi ke Tenggarong di masa hari ini. Tujuh aktor muncul di atas panggung dengan tubuh canggung dan vokal yang nyaris mekanis. Mereka semua bicara dalam bahasa Indonesia.
Salah satu dari mereka, yang mengenakan sorban dan gamis biru, menjelma semacam hulubalang. Sosok ini menanggung anakronisme akut dengan menyebut tanggal 13 April 13 tahun sebelum Hijriah sebagai penunjuk waktu di mana ia berada. Artinya, ia seperti datang dari masa depan hingga tahu bahwa 13 tahun setelah itu akan ada peristiwa Hijrah. Ia juga menyeru-nyeru kaum pujangga untuk berlomba membuat syair yang sekiranya mampu menandingi keindahan kitab suci Al-Qur’an–satu kisah yang mengingatkan kita kepada cerita kaum penyair Jahiliyah yang menuduh kitab suci adalah syair-syair karangan Muhammad sang nabi.
Enam orang aktor kemudian menjadi para pujangga itu, yang bergantian membacakan syair-syairnya (dalam bahasa Indonesia) dengan gaya, intonasi, serta penekanan yang akan segera mengingatkan kita kepada gaya pembacaan puisi dalam lomba deklamasi tingkat SD. Si hulubalang, agaknya, kemudian beralih status menjadi dinding kabah lantaran para pujangga menempelkan (sesungguhnya mengalungkan) kertas-kertas bertuliskan syair mereka ke lehernya, mengingatkan kita kepada Al Muallaqat.
Baca juga: Esai “Homo Digitalis dan Kebutuhan Kita pada Filsafat”
Pusparagam Tegangan
Adegan pembuka tersebut memicu tegangan dalam diri saya, sekaligus mengingatkan saya bahwa Sahur Mayur adalah rangkaian acara Ramadhan. Tegangan tersebut berlapis-lapis. Lapisan paling awal adalah tegangan antara imajinasi pertama saya dengan pertunjukan yang terjadi di depan mata. Yang awal ini tidak terlalu penting, sesungguhnya, lazim terjadi, dan memang niscaya terjadi. Harapan pemirsa dan apa yang terjadi di panggung adalah sesuatu yang memang berjarak.
Yang menarik justru tegangan yang terjadi di pertunjukan itu sendiri. Tubuh-tubuh canggung aktor, yang salah satunya keluar dari lingkaran cahaya lampu dan memilih sudut gelap yang tak terlihat, agaknya adalah respons alami tubuh Kalimantan hari ini ketika mesti menanggung dan menghidupkan tubuh Arab dari masa seribu empat ratus tahun lampau.
Sebuah kecanggungan yang tak terjembatani. Tegangan ruang dan tegangan waktu yang terus bertikai sepanjang adegan awal – tegangan yang akan bertambah jika, misalnya, kita mempersoalkan masalah bahasa, gaya syair yang digunakan, konteks sosial politik di Arab pada masa itu, dan lain sebagainya.
Tegangan ini, sepertinya, berusaha diatasi pada adegan selanjutnya, ketika latar waktu dan tempat tiba-tiba melompat, ke Kalimantan hari ini, seolah tanpa ancang-ancang. Seorang perempuan dengan baju tidur dan bandana berkuping seperti tikus muncul dan meminta quote-quote untuk dirinya sendiri agar ia terbebas dari persoalan-persoalan mutakhir semacam isu kesehatan mental dan sebagainya. Aktor-aktor yang sebelumnya kaku kemudian hadir dengan tubuh yang rileks (atau tepatnya, lebih rileks dari sebelumnya), dialog-dialog lebih cair, dan Fiersa Besari datang entah dari mana untuk bernyanyi dan menggombal.
Lirik lagu Letto, Permintaan Hati, dibacakan seperti puisi dan ayat 227 As Syu’ara dilantunkan sekaligus memberi garis tebal kenapa pertunjukan ini diberi judul As Syu’ara.
Tegangan belum berakhir ketika pertunjukan Teater Bastra ini selesai, setidaknya dalam kepala saya. Lakon ini, agaknya, adalah lakon yang didaktis, yang menggembol amanat dan pencerahan agar para pujangga tidak melebihi batas, agar syair (dan barangkali semua jenis kesenian) selaras dengan ajaran agama dan kitab suci, agar apa yang disampaikan ayat 227 As Syuara tersebut terdakwahkan–Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
Satu lakon yang mungkin cocok dibawakan di bulan Ramadhan. Namun, tegangan dalam kepala saya bergerak di luar itu. Menjelma tegangan antara syair dan quote – masa lampau dan masa kini. Kita sama tahu, bahwa hari ini, akibat gaya pergaulan di media sosial, orang-orang mulai malas membaca panjang. Satu fenomena yang menyebabkan massifnya unggahan tentang quote.
Quote bahkan–dalam beberapa kasus–mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya adalah kutipan dari teks yang lebih panjang menjadi kalimat singkat yang merdu dan manis dan bijak yang lahir dan berdiri sendiri. Bukan lagi kutipan. Tegangan itu seperti berbisik: “Syair sudah mati, ini zaman quote.”
Apakah pergerseran semacam ini yang menyebabkan buku puisi tak laku di pasaran? Saya tidak tahu. (bersambung…)




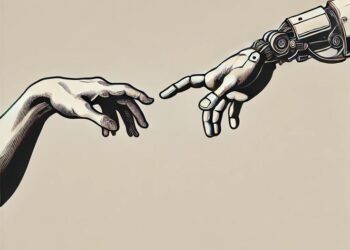












Comments 1