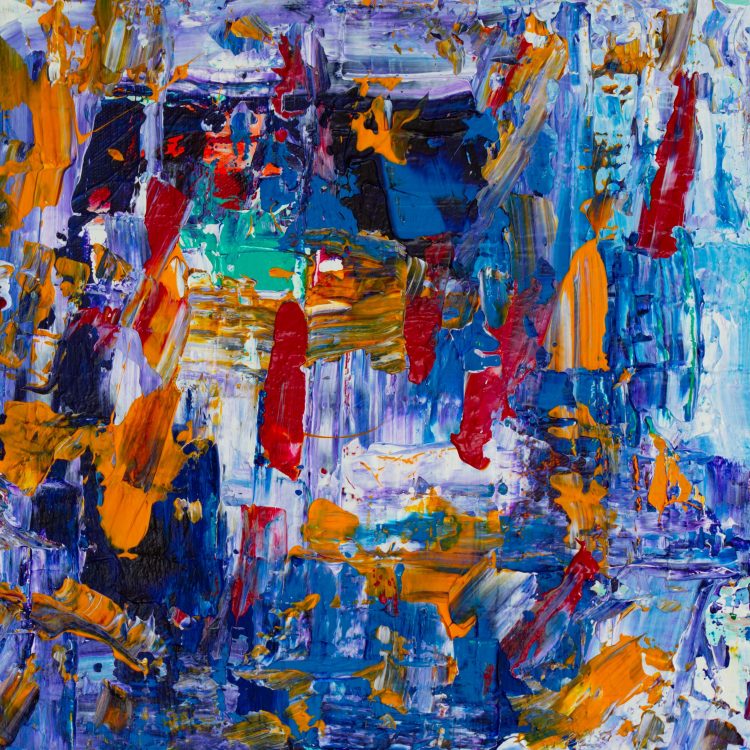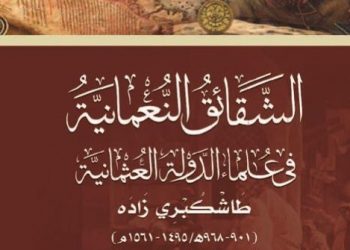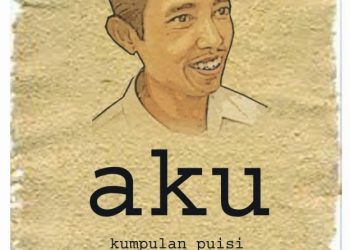Dua puluh tahun merantau di luar negeri, rupanya telah memberikan sensasi istimewa bagi Prof Dr KH Abdul Syakur Yasin, MA. Seorang Kyai yang khas dengan bahasa panturan itu mengakui, bahwa ia sempat merasa menjadi seorang makhluk yang hidup sendirian di tiga puluh tahunnya selama kembali ke Indramayu, kampung halamannya. Pasalnya, masyarakat telah mendedahkan kepadanya sebuah kebudayaan berpikir sinonim. Ia menyebutnya sebagai tadarruf watut taradduf, atau similarisme. Ialah cara berpikir untuk menyama-nyamakan sesuatu. Padahal, adalah penting bagi setiap makhluk untuk membedakan sesuatu dengan yang lain, sebab menurutnya, setiap perubahan menuntut terma atau istilah yang baru.
Sebagai analogi, Ia menyodorkan perbedaan dan substansi antara cangkir dan gelas. Bagi kebanyakan orang, cangkir dan gelas adalah hal yang sama. Sebuah alat yang memiliki fungsi yang sama. Kendati keduanya dapat menampung teh dan (atau) kopi, namun cangkir dan gelas adalah dua hal yang berbeda. Esensi dari cangkir adalah sebagai wadah kopi. Sedangkan gelas memenuhi ketepatan sebagai wadahnya teh. Keduanya tetap berbeda dalam hal bentuk, meski beberapa fungsinya tetaplah sama. Sebab itulah cangkir tetaplah cangkir dan gelas tetaplah gelas. Hal inilah yang ingin disoroti oleh Buya Syakur Yasin. Bahwa tidak segala hal yang sama dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang sama, similarisme.
Buya Syakur, begitu ia akrab disapa, kemudian menyodorkan pertanyaan. “Ketika kita bicara tentang keabadian, keabadian mana yang kita bicarakan?”. Dengan wajah tersenyum, ia kemudian menyambung jawaban.
“Sebab daiman tidak sama dengan abadan. Dan abadan tidak sama dengan khalidan. Begitupun juga dengan khalidan, ia tidak sama dengan sarmadan. Yang dijamin abadi oleh Allah adalah al-Dzikr, bukan Al-Quran”, ungkapnya.
Dalam ngaji rutinan yang dilaksanakan bersama Wamimma TV melalu channel youtubenya, bertemakan ‘Agama dan Budaya; Buya Syakur Menimbang yang Fana dan yang Abadi’. Ia mengupas perbedaan antara budaya dan agama sampai pada kulitnya. Bagi Buya Syakur sendiri, apapun yang lahir dan dihasilkan oleh manusia, baik berupa pemikiran dan produk kemanusiaan adalah definisi budaya. Hal ini yang kemudian sering menjadi pokok persoalan di masyarakat Indonesia, dari hukum hingga madzab. Ia mengingat-tegaskan, jangan sampai salah satu dari kita terjebak pada klaim kebenaran, apalagi sampai merujuk bid’ah atau kafir-mengafirkan. Karena pada dasarnya, manusia tidak tahu apa-apa. “Mulut saya terlalu mahal untuk mengecap benar, apalagi sampai mengafirkan sesuatu atau sesiapa”, tandasnya.
Sementara itu, dalam menimbang arti abadi, pengkaji kritik objektif Novel Yusuf As-Siba’i ini menilai, bahwa abadi adalah ketika waktu dan gerakan itu berakhir. Abadi terjadi ketika sudah tiada lagi hitungan waktu yang menandakan saat itu berhenti bergerak. Waktu adalah tiada, yang ada hanya nisbi. Baginya, waktu merupakan produk dari kebudayaan. Dalam menerangkan hal ini, Buya Syakur menjelaskan tradisi dan kebudayaan bangsa Mesir dalam menentukan waktu. Dari mengukur pagi dan siang dengan penggalah, hingga akhirnya tercipta pengukur waktu dari pasir. Keadaan itu berlanjut hingga sekarang, saat manusia tengah difasilitasi dengan gadget sebagai pengukur waktu yang akurat. Penjelasannya tersebut sekaligus menerangkan, bahwa ideologi, agama, budaya, atau bahkan sains, merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri dan menjadi bagian dari arus sejarah bangsa atau budaya lokal, terlebih bahasanya.
Betapa menggelikan, meneropongi fenomena yang akhir-akhir telah melanda Bangsa ini. Dimana tukar-padu, perselisihan, juga fatwa yang membaur-memenuhi beranda media, lalu terdengar di setiap telinga. Hal ini hanya disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang dualisme yang niscaya. Bagaimana mungkin, seseorang dapat memerah telinganya hanya karena mengetahui tradisi Sekaten masih dihidupi oleh warga Surakarta, atau upacara Nyadran yang masih lestari di wilayah Jawa Timuran. Dengan lantang dikatakan bahwa segala tradisi yang masih hidup dan dipercayai oleh masyarakat itu adalah bid’ah, suatu kekafiran terhadap Tuhan. Anak kebudayaan seperti tertukar dengan agama. Sehingga bid’ah dan label haram begitu ringan diucapkan, tanpa memahami asbabun nuzul atau sebab-sebab kehadirannya dan tanpa mengetahui apa dan sesungguhnya maknanya, yakni puncak dari bahasa itu sendiri.
Sebagai kesimpulan, ia menunjukkan sebuah bagan yang diguratnya menggunakan media kertas dan spidol hitam. Dalam bagan lingkaran yang terdiri dari beberapa lipatan, ia menulis kata syariat, akidah, akhlaq, dan yang terakhir cinta. “Kita akan berhenti bertengkar perihal agama ketika sudah sampai dan masuk ke inti agama, ialah cinta”, pungkasnya.
Kata-kata Buya, mengingatkan kita pada kidung cinta Sang Syaikhul Akbar, Ibn ‘Arabi. “Aku beragama dengan agama cinta/ ke manapun ia bergerak, maka cinta adalah agama dan keyakinanku”. Cinta adalah agama itu sendiri. Agama bukan hanya liturgi, melainkan ruh yang menyatu bersama Sang-Ada, melebur dalam Ke-ti-ada-an, menyandar pada kalimat Innalillahi wainna ilaihi raaji’un. Mengabadikan yang Fana, Memfanakan yang Abadi, serupa alasan Tuhan menciptakan bumi dan seisinya.
*) Tulisan tersebut adalah hasil reportase singkat penulis terhadap kajian Buya Syakur Yasin melalui akun youtube dan siaran langsung bersama Wamimma TV.