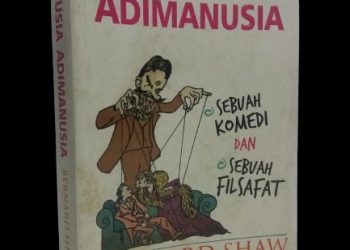“All I am is literature, and I am not able or willing to be anything else.”
― Franz Kafka
Jika kita ingin mendefinisikan perihal seluk-beluk apa itu sastra, sudah tentu tulisan sederhana ini tidak akan cukup untuk membabarkannya. Lagi pula tulisan ini tidak hendak menjelaskan tentang apa itu sastra. Tulisan sederhana ini hanya ingin menjelaskan secara singkat sastra sebagai sebuah jalan ritmis untuk menjadi seorang ‘manusia’. Jika ada yang tidak sependapat dan kurang berkenan pada tulisan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya terhadap sastra.
Dalam kesejarahannya, sastra adalah bagian yang tak terpisahkan dalam setiap kebudayaan masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana di setiap kebudayaan memiliki cerita rakyatnya (folklore) masing-masing. Baik itu cerita lisan maupun tulisan. Setiap karya sastra yang lahir adalah sebuah usaha untuk meperlihatkan kepada kita tentang kenyataan sejarah kehidupan. Tiada karya sastra tanpa sejarah. Sebab karya sastra pada dasarnya dibangun dari inti sejarah. Dan seorang sastrawan sejati akan selalu menolak tirani sejarah.
Saat arus zaman membawa peristiwa-peristiwa yang makin lama semakin mengerikan untuk dibayangkan, setidaknya sastra mampu membawa kita untuk ‘keluar’ dari bayang-bayang itu. Pada era ini, di mana modernitas mencapai aspek puncaknya, dimensi kesusastraan menjadi semakin pudar dalam kehidupan masyarakat. Keindahan dan dimensi didaktis sastra tertutupi oleh gedung-gedung pencakar langit, oleh riuhnya kabar di televisi, kabar di gadget kita, serta gemerlap lampu dan produk–produk material lainnya–pusparagam hasil dari ‘kemajuan manusia’ yang bernama modernisasi.
Namun meski demikian, Emha Ainun Nadjib, saat ia berada di sebuah acara majalah sastra Horison dalam orasi kebudayaannya, beliau masih menaruh harapan dan tak kehilangan semangat pada sastra. Dalam orasinya beliau mengatakan:
“Sastra tidak akan musnah oleh riuh rendahnya negara serta Industri dan kapitalisme yang sangat tidak berpihak pada manusia. Sebab manusia secara alamiah akan sangat membutuhkan sastra untuk mengolah ‘proses perohanian dan pelembutan kehidupan’.”
Berdasarkan perkataan itu, saat daya rawat kesusastraan terasa semakin melemah, maka tugas utama seorang ‘sastrawan’ adalah merawat, membesarkan, serta membumikan kembali kesusastraan pada kehidupan bermasyarakat. Sebab sastra bukanlah barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kaum elit intelektual saja. Sastra harus kembali menjadi bagian dari setiap kehidupan masyarakat pada umumnya. Sastra sejatinya tidak hanya terbatas pada dimensi literasi an sich. Sastra lebih luas dari itu.
Sastra adalah dimensi ritmis perjuangan panjang manusia untuk membebaskan diri dari jeratan-jeratan dan keterikatan berlebih terhadap dunia. Sastra juga adalah senjata manusia untuk dapat berkata tidak pada segala kekuasaan yang ketika belum puas mengatur hidup kita, ingin juga memerintah kesadaran kita secara semena-mena.
Jika kita mengangap sastra sebagai alat untuk kemashuran diri, sastra pun tidak akan berarti apa-apa pada diri serta kehidupan khalayak–kecuali hanya menjadi sebuah mercusuar ego yang menjulang tinggi.
Belajar sastra adalah berproses untuk menjadi manusia yang benar-benar manusia. Karena manusia bukanlah sebuah eksistensi yang ajeg. Bukan entitas stagnan yang seolah sudah selesai. Menjadi manusia adalah proses yang terus berkelanjutan. Dan sastra adalah salah satu alat untuk ‘menjadi manusia itu’.
Seorang Begawan Guru dari India pernah berujar bahwa, “Pertumbuhan diri manusia sejatinya bukan berarti kita terus membesar dalam segala aspek. Pertumbuhan diri manusia adalah saat kita menjadi semakin tipis seperti udara. Dan hal itu bisa ditandai dengan ketika Kehadiran Diri menjadi sangat kuat, namun personalitas ke-aku-an semakin melemah”.
Berdasarkan perkataan begawan tersebut, secara eksplisit sangat jelas pentingnya pengendalian anasir ke-aku-an. Terlebih, ke-aku-an atau keegoisan pada peradaban hari ini sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Manusia dengan ego tingginya tak segan-segan untuk merendahkan, menindas, bahkan membunuh sesamanya. Sastra, yang di mana dalam pendalamannya sangat menitikberatkan pada pengolahan dimensi halus pada diri manusia, pada dasarnya untuk melatih kepekaan diri tentang universalitas kehidupan.
Manusia dengan segala anugrah potensinya mampu merubah tanah dan mendewasakannya menjadi padi, menjadi sayuran, menjadi bangunan dan berbagai macam jenisnya. Bahkan kotoran pun bisa manusia rubah menjadi buah atau bunga, jika kita bisa mendewasakannya ke arah yang benar. Demikian pun dengan sastra. Sastra mampu mendewasakan manusia ke arah yang semestinya sesuai titik koordinat masing-masing.
Manusia adalah lakon utama dalam sejarah, maka secara tidak langsung manusia pun adalah bahan baku dasar dan sekaligus korbannya. Sastra secara mendasar menitikberatkan pada persoalan ini. Sastra pada intinya tidak memiliki misi lain selain merubah manusia. Baik itu secara individual maupun komunal. Berbagai macam karya sastra telah lahir, baik itu yang berbau romantik, bersifat perlawanan, bernafaskan profetik, dan lain sebagainya. Karya sastra akan selalu terikat dengan fakta realitas kehidupan yang terjadi.
Sastra adalah manifestasi perasaan serta gejolak diri manusia dalam menyikapi kehidupan. Sastra mengendarai kendaraan yang bernama bahasa. Bahasa sastra harus senantiasa menjebol bahasa keseharian. Karya sastra, terutama puisi, di mana kata-kata diubah ke dalam unit-unit ritmis maupun imaji-imaji metafor, jika dalam perkataan Octavio Paz–seorang sastrawan Meksiko–berfungsi untuk “melebur kenyataan yang bagi kita tampak bertentangan dan tidak sederhana menjadi satu kesatuan makna indah yang utuh”.
Hari ini ketika begitu banyak manusia-manusia yang heterogen “diseragamkan” oleh cambuk propaganda dan virus-virus kepopuleran, karya dan kreasi sastra seolah terpukul keras dan memasuki dunia persembunyian. Menyikapi realitas kehidupan yang sangat begitu paradoks dan kompleks, kehadiran sastra sesungguhnya mampu menjadi oase pelepas dahaga di tengah gurun-gurun ketidakpastian.
Aktivitas sastra harus kembali menemukan semangat purbanya. Ia harus mulai turun menghujani dan mengguyuri kehidupan bermasyarakat yang semakin kering, kasar, gersang dan seolah beralih menjadi kehidupan robotik.
Mari kita refleksikan sejenak betapa hebatnya pengaruh kumpulan kata-kata di kitab-kitab suci yang ada di dunia. Baik itu Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Budhha, dll. yang sejak puluhan ribu tahun silam hingga saat ini, semua manusia di kolong langit jika meminjam istilah Pak Achdiat K. Mihardja berada dalam pengaruh “mahkota sastra” tersebut. Bahkan seorang pemikir asal mesir bernama Nasr Hamid Abu Zayd pernah mengatakan bahwa kehidupan manusia jika disingkat adalah “haddlaratun nash” (peradaban teks) yang pada akhirnya melahirkan “muntaj tsaqofi” (produk budaya).
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat tanpa dibarengi dengan kesadaran tinggi akan kehidupan, lambat laun romantisme dan kasih sayang akan semakin pudar. Dan jika romantisme hilang maka saya berani mengatakan bahwa mahluk yang bernama manusia itu telah punah. Sebab jika sebuah peradaban sangat memberhalakan sifat-sifat materialistik dalam kehidupan, otomatis manusia akan terjebak dalam sebuah negeri bebal budaya. Dan sejarah mencatat: bahwa kebebalan budaya nyaris selalu menjadi biang dari kepunahan peradaban manusia.
Kiranya untuk menutup tulisan singkat ini saya akan mengutip puisi dari seorang penyair besar Meksiko:
“Aku tidak pernah sendiri
Aku selalu bicara kepadamu
Kau selalu berbicara kepadaku
Aku bergerak dalam gelap
Menanam lambang-lambang”.