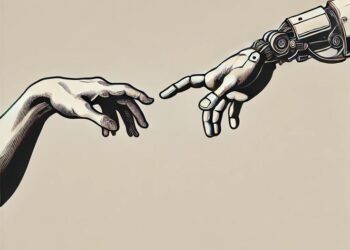Jika bulan Juni sudah kepunyaan Sapardi, Juli adalah milik Hemingway. Pasalnya, suara tangis bayi-Hemingway pecah di bulan yang sama (21 Juli 1899) dengan guguran bunga kematiannya di moncong senapan (2 Juli 1961). Dan kata-kata di judul menjadi residu dari keseluruhan hidup sastrawan maskulin yang terkenal dengan gaya bahasa jitu dan efektif itu.
Jauh sebelum namanya mekar usai memenangi Pulitzer dan Nobel Sastra, Ernest Hemingway getol menulis feature soal memancing. Ia mempublikasikannya di majalah dan koran-koran seperti The Toronto Star Weekly, The Toronto Daily Star, Holiday, dan majalah Esquire. Itu bermula sejak 1920, ketika usianya masih 21 tahun.
Disiplin jurnalistik dan pengalaman-bersentuhan-langsung menyerbuki karya sastranya yang terkenal dengan kalimat-kalimat efisien, terarah, tidak banyak fafifu, namun sarat kedalaman. Dua bekal itulah yang kini semakin raib; digantikan interaksi layar-jauh dan pengalaman virtual—yang tanpa bau, tanpa rasa, tanpa picingan pedih di mata akibat kepulan asap konflik atau becek lumpur, karena asap dan lumpur di layar hanyalah gumpalan data piksel di ponsel genggam. Wajar apabila karya sastra kini jauh lebih banyak yang permukaan, festivalis, akrobat diksi, terfragmentasi, eksperimen dangkal, dan hanya segelintir yang mendalam.
Kemendalaman itu, pada karya-karya Hemingway, salah satunya diperoleh lewat memancing. Baginya, aktivitas memancing bukan sekadar hobi, melainkan meditasi aktif. Ruang privat di mana dunia boleh runtuh, negara-negara silakan berperang dan menjejer mayat-mayat di Italia, tapi kemesraannya dengan lompatan ikan trout di ujung joran takkan terganggu, “hanya milikku seorang.” Itulah ekstase di ujung senar.
Perihal memancing, ia bisa dikata obsesif. Memancing tidak hanya bersifat rekreasional, Hemingway juga mencatat log, data-data cuaca, dan memperlakukannya sebagai sains terkait jenis-jenis marlin dengan tingkat kuriositas ekstrem. Sebagai buktinya, ia pernah bekerja sama dengan ilmuwan kelautan soal migrasi ikan, bernama Dr. Henry Stratemeyer.
Kendati banyak rintangan dan rasa letih saat memancing, baik saat di laut memburu marlin maupun di sungai melecut trout, Hemingway mengkhusyukinya. Ia penganut diktum “grace under pressure”. Bahwa ada martabat dalam penderitaan. Dan memancing baginya adalah latihan eksistensial, bukan hiburan an sich.
Anasir itu terkandung di novela monumentalnya, The Old Man and the Sea. Banyak yang menafsirkan sosok Santiago dalam novela itu adalah Hemingway. Padahal, orang akan menyimpulkan berbeda jika ia membaca surat On the Blue Water: A Gulf Stream Letter bertitimangsa April 1936 terbit di Esquire (versi terjemahan An Ismanto berjudul “Di Air Biru: Surat dari Gulf Stream” terbit di Penerbit Circa, 2018). Di surat itu Hemingway menulis tentang sosok tua yang menjadi embrio kisah bertahun-tahun mendatang: lelaki tua yang pergi memancing, sendirian, bermodal sampan di lepas pantai Cabanas. Ia pulang dengan tulang-belulang Marlin raksasa dan wajah bersisa tangis. Kisah itulah yang diolahnya sedemikian rupa dan meledak di blantika sastra dunia.
Mengenangnya, Tanpa Meneladani “Akhir”-nya
Pada bulan Juli ia lahir sekaligus mati. Mati di tangannya sendiri. Hemingway adalah contoh tragis dari seseorang yang hidupnya tampak penuh petualangan dan kejayaan, namun justru (diam-diam) memeram keperihan batin yang sunyi. Ada langgam kehampaan di sana, gunung es penderitaan, kesepian yang memekik, perang batin, perang harfiah, trauma, dan absurditas hidup yang manunggal dalam satu tubuh.
Akhir bunuh diri semacam itu, mirisnya, masih mengintai kita di zaman ini. Baru kemarin saja di Jogja dekat sungai Oya, Selopamioro, ada pelajar SMP gantung diri. Dan setahun terakhir tidak sedikit kasus-kasus semacam itu. Depresi telah menjadi wabah. 300 juta orang di dunia menderita karenanya. Di tanah air kita, depresi dan krisis kesehatan mental cukup mengkhawatirkan, tak peduli tua maupun muda. Lalu apa kaitan antara “sastra, mancing, dan bunuh diri”—selain representasi hidup Ernest Hemingway?
Dua yang pertama mampu mencegah terjadinya yang terakhir. Sastra dan memancing memiliki fungsi terapeutik bagi kesehatan mental. Keduanya dapat menjadi jalan keluar non-klinis; menciptakan ruang refleksi, relaksasi, kemesraan dengan alam, mengasah sabar dan kepekaan (empati), serta melatih kembali fokus yang telah direnggut medsos. Sastra dan memancing bukan sekadar hobi; keduanya adalah sepasang jalan sunyi yang menyelamatkan jiwa.

Di tengah zaman yang Byung-Chul Han sebut sebagai “masyarakat kelelahan akut” (burnout society) dan hanyut dalam melakoni auto-eksploitasi (memeras diri sendiri), sangatlah penting untuk merebut waktu, menggembalakan ritme hidup yang lebih masuk akal dan perlahan. Di sekujur zaman yang kebak ancaman otak membusuk (brain-rot) karena paparan digital sekarang ini, kita perlu beralih dari kesibukan vita activa masyarakat-pencapaian ala neoliberal menjadi vita contemplativa di mana masih tersisa ruang personal untuk merenungkan hidup yang serba cepat. Izaak Walton dalam The Compleat Angler (1653)—karya klasik yang dipuji-puji Hemingway—pernah menulis: “Tuhan tak pernah menciptakan sebuah rekreasi yang lebih tenang, sunyi, dan murni selain memancing.”
Namun, sayangnya, kenikmatan itu berakhir karena Ernest memecahkan kepalanya sendiri. Dan tiga patah kata di judul menjadi sambung tanpa tanda koma: “sastra memancing bunuh diri”? Apa memang jangan-jangan begitu? Baik bunuh diri harfiah, maupun metaforis: bunuh diri karier, bunuh diri politik, sosial, ekonomi, hingga bunuh diri relasi romantik dan bunuh diri keluarga.
Namun, terlepas dari itu, kalau boleh saya memberanikan diri berasumsi: barangkali Ernest memang terlalu memburu adrenaline rush. Ia sakau pada pertarungan dengan ikan-ikan jumbo, sehingga kurang mampu menikmati yang serba kecil, remeh, kurang berguna. Singkatnya, Hemingway lupa pada “filsafat jeda sejenak” (Zwischenzeit) dan ajaran Zhuangzi tentang “seni menghargai yang tak berguna”. Dan semua ini ada pada praktik microfishing.
Hemingway bisa saja batal bunuh diri jika ia punya pengalaman memancing ikan-ikan mungil (microfishing) bersama bapak-bapak random di Jogja. Dengan senar nol koma nol enam setipis rambut, joran pecut lentur dan kail mungil, mereka mengeja aneka jenis sisik ikan wader, uceng, hingga anakan nilem. Selera humor mereka menghangatkan hati. Apalagi mendengar celetukan receh, “Ikan di Jogja sudah pada sarjana, Nest! Wong kota pelajar, og.” Belum yang di tingkat seru-seru-saru seperti, “Awas lurr … ada angin puting berliur! Puting berliur!” Walau terkesan seksis, tapi siapa yang sanggup tidak ketawa?
Lalu, boleh jadi Hemingway lekas terpanggil meneliti, melakukan sensus ikan dan brand-audit perusahaan pencemar terbesar terhadap sungai-sungai di Indonesia. Kemudian ia berorasi, menulis di koran-koran, juga sambat di Metafor, menolak tambang yang merusak ekosistem sungai dan laut tempatnya “menyelamatkan ikan yang tenggelam”, untuk hanya mendapat cemooh dari satu tokoh ormas: “Wahabi Lingkungan!”
Maka, lewat memancing, di situlah letak kenikmatan hidup di tengah kacau-mendungnya negeri ini. Ia akan tersentak ketika bapak-bapak random mengajarinya cara meracik umpan dari EkoMie, Roti Klik, hingga pelet campur KukuBima dan Masako, untuk memanen ikan-ikan sarjana di Jogja, mulai dari jenis ikan putihan, lepasan kolam, hingga uceng. Dengan melakoni microfishing, akan terbit kecenderungan meromantisasi yang kecil, remeh, tak penting. Dan sastra memberi bobot dan nyawa kepada yang remeh, kepada yang sepele.
So, in this economy and current politics, alih-alih menyerah pada hidup, mending baca karya sastra, lalu angkat joranmu. Tinggalkan sejenak ponselmu, lekaslah pergi ke kali-kali di desamu, mengenang kembali masa kecil kita bersama. Setidaknya, sekalut apa pun masalah hidupmu, di bulan Juli ini kita akan kembali mendapat satu alasan baru untuk tetap hidup–selain menanti ending One Piece–dengan berikrar: “Aku takkan mati sebelum strike 10 jenis wader di Jogja dan sidat sebesar paha Si Bahlil!” Lalu, sebagaimana lelaku Hemingway, tulis kisahmu sendiri—tanpa bunuh diri.[]