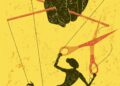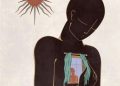Bagi orang Jawa, makan tidak sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi memaklumatkan cara pandang dan laku menghargai kehidupan. Saat “ritual” makan digelar, tata krama harus selalu dijaga. Misalnya, santun di meja makan, tidak berisik, perlahan namun tidak lambat dan berpantang untuk makan di sembarang tempat. Orang Jawa memperlakukan makanan sebagai anugerah. Makanan dijaga sebaik-baiknya sehingga orang jawa tabu untuk membuang-buangnya. Sebuah mitos tetapi sarat nasehat kerap kita dengar: yen mangan kudu dientekke mundhak pitike podho mati (kalau makan harus dihabiskan, kalau tidak ayamnya mati). Juga mitos yang lain: ora ilok yen mangan neng ngarep lawang mundhak angel jodhone (tidak baik kalau makan di depan pintu, nanti sulit mendapatkan jodoh).
Apa yang ada di balik mitos ini sesungguhnya adalah jalan orang jawa untuk menghargai makanan. Dengan menghargai makanan, maka secara tidak langsung penghargaan terhadap hal-hal lain muncul. Tanah, dimana tetumbuhan ditanam, perlu dirawat. Tanah memberikan kehidupan, makanan. Air, darimana makanan memperoleh asupan, merupakan entitas penting yang perlu dijaga. Hutan, sungai, dan sebagainya tak boleh mengalami kerusakan. Secara lebih luas dapat diartikan bahwa manusia perlu menjaga bumi seisinya, bahkan alam semesta. Hal itu tidak lain karena manusia dan alam memiliki ikatan timbal balik, saling terikat satu sama lain.
Sudah umum pada masyarakat bahwa laku spiritual juga diwedarkan melalui makanan. Wujud rasa syukur atas karunia Tuhan dengan panen yang melimpah dimanifestasikan dengan acara sedekah bumi. Ketika hasil laut melimpah masyarakat menggelar sedekah laut, atau “perayaan-perayaan” lain serupa itu. Semuanya dilakukan dalam kerangka menghargai makanan, dan rentetan sumbernya, yang telah diberikan bagi kehidupan. Pada intinya orang Jawa tidak hendak menjadi manusia yang mengingkari nikmat.
Meski demikian, sebagai sesuatu yang dicari dan mengenyangkan, tidak lantas makanan diagung-agungkan. Ada batasan-batasan di sana. Sebab itu kita menjadi mafhum bahwa filosofi Jawa mengundangkan agar manusia tidak menjadi tamak, baik secara faktual maupun metaforis. Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java (2008: 64) pernah memberikan kesaksian begini: “meskipun sumber alamnya melimpah, orang Jawa tampaknya berhati-hati dalam hal makanan, mereka tidak suka makan banyak. Makan enak berarti makan dengan lahap, demikian istilah mereka, dan mereka merasa puas dengan hidup secukupnya.”
Demikian pula makanan juga menjadi metafora bagi orang Jawa dalam hubungannya dengan kekuasaan. Lagu Gundul-Gundul Pacul yang populer itu menisbatkan setiap pemimpin agar tidak gembelengan atau sombong saat nyunggi wakul (diberi amanah untuk memimpin banyak orang). Karena wakul, wadah bagi makanan itu, dengan sendirinya mencerminkan pusat bagi kebutuhan makan banyak orang.
Sehingga jika “wakul ngglimpang”, maka “segane dadi sak ratan”. Saat orang yang dijadikan pemimpin tidak lagi dapat dipercaya, maka kedudukannya tidak membawa manfaat, tidak memberikan kesejahteraan. Dengan kata lain, pemimpin yang nyunggi wakul (menanggung kesejahteraan banyak orang) perlu berhati-hati atau memegang teguh amanah agar tidak jatuh (ngglimpang). “Sega”, dalam arti makanan maupun kekuasaan, merupakan titipan yang patut dijaga, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Dalam konteks yang lebih luas, makanan bisa dikaitkan secara simbolis bagi kebesaran sebuah bangsa. Bangsa yang besar berarti bangsa yang mampu menyediakan makanan bagi rakyatnya, yang berarti tercapainya kesejahteraan. Di sisi lain bangsa yang besar juga bangsa yang mampu menghargai makanannya sendiri. Sebagaimana pernah dikisahkan Cindy Adams (2014), suatu kali Bung Karno pernah geram pada orang-orang di sekelilingnya karena menganggap makanan Indonesia kurang pantas dihidangkan kepada orang-orang Eropa yang menjadi tamunya.
Bung Karno menolak anggapan dan rasa rendah diri itu. Dengan nada marah ia berujar, “kita mempunyai penganan yang enak-enak”. Di sini, Bung Karno agaknya ingin menampilkan makanan sebagai simbol nasionalisme yang gagah. Sebuah bangsa tidak mungkin dihormati bangsa lain tanpa menghormati dirinya sendiri.
Demikianlah bahwa makanan bisa dinikmati dan dimaknai melalui banyak hal. Apapun kondisinya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, makanan atau pangan atau lebih luas adalah kebutuhan, menjadi sesuatu yang perlu dikelola dengan bijak, baik dalam konteks diri sendiri maupun masyarakat, bangsa dan negara. Terimakasih. Wallahu a’lam.[]
Referensi:
Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta: Yayasan Bung Karno dan PT Media Pressindo, cet. ke-3, edisi revisi, 2014.
Thomas Stamford Raffles, The History of Java, Yogyakarta: Narasi, 2008.