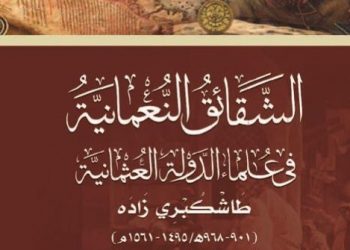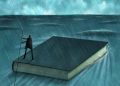Dan inilah yang mungkin banyak dari kawan saya sudah mendengar, saya pernah ditemui Ratu dari Para Ratunya Bangsa Jin. Tapi tenang, sekarang tahta itu sudah ada di saya. Jadi sekarang ini saya adalah Raja dari Bangsa Jin. Hormati saya!
Perempuan, mungkin berusia tiga puluhan tahun. Datang di sore hari yang mana saya sedang santai sebab belum ada pelanggan. Mulanya dia berlagak biasa saja, sebagaimana pelanggan kedai pada umumnya. Pesan minuman, lantas mencari tempat duduk. Setelah menentukan tempat duduknya dengan diletakkan tas miliknya, dia tak kunjung duduk. Berjalan kesana-kemari seperti orang gelisah. Saya biasa saja, masih membikinkan pesanannya.
Bel tanda pesanan sudah jadi saya dentingkan. Kebetulan dia sedang mondar-mandir tak jauh dari tempat pesanan sudah jadi. Saya panggil, “Mbak, ini pesanannya sudah jadi.”
“Lho, ya dianter ke tempat saya dong, Mas. Saya ini pelanggan, kok disuruh ambil sendiri, gimana toh.”
Untung saja nada bicaranya guyon, bukan marah betulan. Dia mendekat ke minuman pesanannya, dan di situ juga dia mengaduk minumannya. Yang bikin saya gatal untuk bicara, adalah cara mengaduknya yang berlebihan, sampai tumpah-tumpah membasahi nampan.
Karena sebelumnya dia terlihat guyonan, maka saya guyoni juga, “Ada masalah apa, toh, Mbak? Kok ngaduknya ndak bisa biasa.”
Ndilalahe, dia bilang, “Aku ini marah betul. Marah betul dengan yang namanya Cak Nun. Di mana orangnya? Saya mau ketemu. Mau saya labrak. Orang kok bisa kayak gitu.” Walah, siapa pula yang ndak kaget dengar dia bicara seperti itu. Yang tadinya dia nampak friendly, sekarang jadi orang lain yang dipenuhi amarah.
“Ada masalah apa sama Mbah Nun, Mbak? Kita bicarakan dulu.”
“Kamu siapanya Cak Nun? Siapa yang punya warung ini? Siapa yang punya tempat ini? Saya mau ketemu siapapun yang ngurus tempat ini. Mau saya labrak itu yang namanya Cak Nun. Kamu siapa di sini? Kamu siapanya Cak Nun?” Dengan sentakan-sentakan nada tinggi amarahnya.
Wah, ini kesempatan saya berlatih teater, batin saya. Tak lama, saya bicara dengan tegas, dengan tatapan mata yang tajam, “Saya yang ngurus warung ini. Saya cucunya Mbah Nun. Saya yang jaga di Kadipiro ini. Sampean ada urusan apa?”
Dia masih menantang, “Beneran kamu cucunya Cak Nun? Apa buktinya kamu cucunya?”
“Memangnya apa yang mau dibuktikan? Saya tunjukkan identitas? Atau mau adu keilmuan dengan saya?” Untung saja dia tidak meladeni adu keilmuan yang saya tawarkan, sebab saya ini jelas tidak handal apa-apa.
“Saya ini marah betul. Kok bisa-bisanya Cak Nun sewaktu pengajian mesti misuh-misuh, entah asu, bajingan, dan teman-temannya. Setiap pengajian di Kasihan itu pasti misuh-misuh terus.”
“Lho, mana pernah ada pengajian? Wong itu Maiyahan kok, sinau bareng, bukan pengajian.” Dia jeda bicara agak lama.
“Kalo saya sendiri yang dengar, ya ndak masalah. Tapi saya ini setiap pengajian mengajak dua anak saya yang masih kecil. Masak iya anak-anak saya masih kecil sudah dengar pisuhan-pisuhan begitu? Bagaimana nanti kalau dicontoh? Apa misuh itu baik?”
Akhirnya saya ajak dia ke tempat duduknya, supaya lebih nyantai dikit. Sekitar empat jam dia ada di kedai. Bukan cuma ngobrol dengan saya, tapi juga ke kawan kerja saya yang lain. Tapi tetap, saya lah yang mendapat dominasi obrolan selama empat jam itu. Cerita ngalor-ngidul dan berdebat ngetan-ngulon. Selama empat jam itu, intinya cuma satu: dia ingin ketemu Mbah Nun.
Karena Mbah Nun pun saat itu di luar kota, saya tawarkan dia untuk menitipkan pesan saja. Dan setelah dititipkan, ya sudah, tidak ada problem lagi, katanya. Cuma ingin minta maaf karena berpikiran dan marah kepada Mbah Nun seperti tadi. Tapi dipikir-pikir, marahnya itu ke saya, bukan ke Mbah Nun. Dia pamit.
Sekitar dua-tiga hari setelah itu, dia datang lagi. Sekitar waktu maghrib dia datang. Dan ya, saya meladeninya lagi. Kebetulan malam itu ada acara internal di Pendopo, yang letaknya tak jauh dari kedai. Suara-suara dan sebagian ruang masih bisa didengar dan dilihat dari kedai. Dia ingin betul dan memohon-mohon kepada saya untuk bisa ikut ke Pendopo. Saya bilang saja, kalau itu acara internal.
“Kalau kemarin sampean bilang sampean itu tresno sama Mbah Nun, ndak usah ikut kesana. Percaya sama saya.”
Berhasil saya meyakinkan. Tapi datangnya kali ini ternyata tidak sendirian. Dia diikuti oleh Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Nyi Ratu Kidul, dan semua Nyi-nyi yang ada di Yogyakarta, katanya. Dia merasa terpojok karena disuruh oleh Nyi-Nyi itu untuk menjadi Ratu mereka. Ratunya Para Ratu. Gimana ndak pening?
Dia amat merasa terpojok bukan karena tahtanya. Tapi karena para Ratu itu tadi ingin belajar Islam ke dia. Para Ratu sudah masuk Islam, tapi ingin belajar Islam ke dia sendiri. Dia keberatan karena merasa belum cukup ilmu untuk mengajarkan Islam ke mereka. Seperti yang saya duga, dia ingin menitipkan para Ratu itu kepada Mbah Nun, untuk diajari Islam. Dia ingin lagi ketemu dengan Mbah Nun. Saya tahan-tahan betul agar dia tak nekat menuju ke Pendopo yang sedang menjalankan Hizib Nashr waktu itu.
Akhirnya saya tawarkan, “Mbak, begini saja. Saya bisa mengajak jin-jin itu ke Mbah Nun, tapi ada syaratnya.”
“Bagaimana, Mas?” Jawabnya dengan tatapan kepo.
“Saya minta tolong, jin-jin itu ditinggal di sini dulu sebelum anda pulang. Atau pasrahkan ke saya dulu saja. Baru setelah itu saya sowankan ke Mbah Nun, beliau bisa menerima atau tidak.” Dia nurut, tak lama setelah itu dia pamit.
Besoknya? Jelas datang lagi, dong. Dia mengkonfirmasi kelanjutan perihal jin itu.
“Bagaimana, Mas? Mbah Nun bisa mengajari jin-jin itu?”
Untung saja, sore sebelum dia datang, saya dikasih ide Allah untuk menjawab pertanyaan semacam itu,
“Saya sudah ketemu beliau, Mbak. Tapi mohon maaf, beliau belum bisa menerima jin-jin tadi. Sebab sudah banyak yang ikut beliau, nanti malah ndak bisa mengajari dengan baik.
“Lho, terus gimana, Mas? Kok gitu, toh?”
“Kata Simbah, jin-jinnya biar saya saja yang bawa. Biar belajar sama saya saja. Saya dipasrahkan untuk mengurus dan mengajari Islam ke mereka.”
Dia bertingkah seperti betul-betul lega, plong, sumringah, bahagia, dan kesenangan-kesenangan lain. Senang sekali kalau dia sudah tak diikuti jin-jin itu lagi. Akhirnya dia melakukan gerakan-gerakan tangan seperti ritual, yang katanya memberikan tahta keratuannya kepada saya. Dan ya, mulai malam itu saya sah menjadi Raja Bangsa Jin!
Apa dengan begitu sudah selesai? Sudah tidak pernah ke sini? Oh jelas tidak. Setiap seminggu sekali dia ke sini. Bedanya, dia tidak lagi ngebet untuk ketemu Mbah Nun. Cukup ketemu saya saja, beres. Dengan cerita-cerita bawaannya yang tak kalah waw.
Maka saya merangkap tiga tugas di Kadipiro sekarang ini; tukang seduh kopi, satpam, dan juga raja bangsa jin.
Bilamana ada kesempatan untuk sowan ke Mbah Nun, saya betul-betul ingin minta maaf karena mengada-ada konfirmasi beliau terhadap dunia jin yang menyebabkan saya lah rajanya sekarang. Masih banyak dan variatif ‘Para Pencari Mbah Nun’ selain beberapa yang sudah saya ceritakan di atas. Prinsip saya sederhana, mereka butuh seseorang yang mendengarkan apa keluh kesahnya. Maka berikanlah panggung kepada mereka untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya, berikan ruang dan waktu untuk mengakui keberadaan mereka.
Bukan tanpa sebab mereka seperti itu, banyak kemungkinan yang mendorong mereka hingga terkena sisi psikologisnya. Dengan bermacam-macam modus yang saya jumpai, maka tak lain mereka dan saya sendiri adalah pengungsi peradaban. Mengungsi di balik sebuah masa yang orang-orang merasa maju, merasa lebih modern, merasa lebih unggul dibanding dulunya. Tertendang oleh peradaban. Peradaban yang maju ke belakang, mundur ke depan.[]