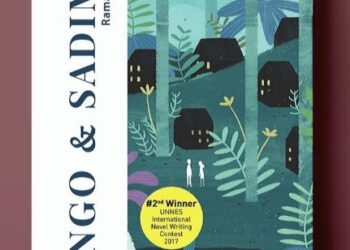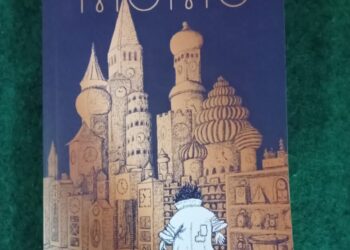Deretan kasus perundungan akhir-akhir ini terus bermunculan. Belum lama ini ramai tajuk berita seputar kasus perundungan di Binus School Serpong, kemudian disusul penganiayaan yang menyebabkan wafatnya seorang santri di Kediri. Masih terpaut waktu yang berdekatan, ada terungkap lagi kasus perundungan di Batam. Itu pun masih banyak lagi kasus yang belum terekspos ke media.
Kasus perundungan di Indonesia ini memang serupa gunung es. Lambat laun kian muncul ke permukaan. Data dari KPAI menyebutkan terdapat 141 pengaduan kasus pada awal 2024. Dari seluruh aduan tersebut, setidaknya 35 persen di antaranya terjadi di sekolah. Sedangkan SIMFONI KEMENPPA 12 Maret 2024 menunjukkan angka yang lebih getir lagi. Terdapat sebanyak 228 kasus dan 287 korban perundungan yang ada di sekolah.
Tak ketinggalan, Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA), Kemendikbudristek, tahun 2021 menemukan bahwa 24 persen anak didik mengalami perundungan di sekolah. Dengan demikian, sekolah maupun lembaga pendidikan belum menjadi ruang aman yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta perundungan.
Data-data di atas saya telusuri sejenak setelah membaca artikel Mbak Afif Hidayatul Mahmudah tentang maraknya perundungan serta rendahnya budaya literasi. Saat itu momennya bertepatan dengan ketika saya sedang terengah-engah menyelesaikan novel Heaven karya Mieko Kawakami. Buku ini terbit pertama kali di Jepang tahun 2009. Kemudian pada Desember 2023, KPG mengalih-bahasakan novel tersebut ke dalam Bahasa Indonesia melalui ketekunan dan ketelatenan Ribeka Ota sebagai penerjemah.
Penderitaan Tokoh Utama
Novel ini memiliki alur cerita yang berjalan maju dengan dibungkus dalam 9 bagian. Dari 9 bagian tersebut, Kawakami konsisten menggunakan POV (sudut pandang–peny.) dari orang pertama, yaitu sang narator. Kepiawaian dan keberpihakan Kawakami pada korban nampak di sini, sebab ia tak menyebutkan nama tokoh utama dalam novel ini, dari awal hingga akhir. Justru nama-nama perundung disebutkan dengan jelas.
Tokoh utama “aku” dalam novel merupakan seorang anak berusia 14 tahun yang memiliki mata juling, sehingga ia dirundung dan diberi julukan “Lonpari” (London-Paris). Julukan itu diberikan karena tatapan matanya diibaratkan yang satu melihat ke London, dan satu mata lainnya melihat ke Paris.
Petualangan “aku” dalam novel ini bermula saat ia menemukan secarik kertas bertuliskan “Kita sekutu” dalam kotak pensilnya. Tak dinyana, kertas tersebut rupanya dari teman sekelasnya yang bernama Kojima.
Kojima sendiri merupakan siswi sekalasnya yang kerap dirundung—sama sepertinya. Mereka berdua pun kerap berkirim surat dan beberapa kali bertemu. Mereka disatukan nasib yang sama. Yaitu sama-sama dirundung dan memiliki latar belakang keluarga yang masing-masing memiliki konflik. Dari sini jelas bahwa Kawakami—seperti pada novelnya yang lain, Susu dan Telur—selalu sukses meramu kompleksitas manusia dan tidak mengabaikannya begitu saja.
Adapun para perundung mereka berdua adalah hampir seluruh teman sekelas. Tetapi yang paling menonjol (dalam artian yang paling mendominasi) ialah Ninomiya dan gengnya. Selebihnya ada pula Momose yang absurd. Jenis perundungan yang dilakukan pun bukan hanya perundungan verbal, melainkan perundungan fisik.
Pada tulisan ini sengaja tak saya tuliskan perundungan fisik seperti apa yang dialami tokoh aku dan juga Kojima, sebab saat membaca, saya acapkali dibuat mual. Sungguh mengerikan dan tak terperi. Tak terbayangkan betapa anak-anak yang mulai memasuki fase remaja bisa berlaku sekejam itu.
Kawakami juga tak mengabaikan aspek usia dalam novelnya. Seperti, misalnya, tokoh aku yang bermasturbasi dikarenakan usia tokoh yang sudah memasuki fase pubertas. Lalu adegan tokoh aku yang dipaksa melakukan hubungan seksual dengan Kojima oleh Ninomiya dan gengnya.
Adegan itu sekaligus menjadi klimaks perundungan dari novel ini. Setelahnya, sang tokoh “aku” tak pernah lagi bertemu Kojima dan ia pun melakukan operasi mata sehingga tidak lagi mengalami kejulingan pada matanya.
Pergulatan Makna
Sebagai seorang anak yang berusia 14 tahun, pencarian makna hidup dan jati diri akan menjadi hal yang wajar. Begitu pula tokoh aku dan Kojima. Dalam obrolan mereka—baik langsung maupun dari berbalas surat—pencarian akan makna hidup dan pertanyaan “apakah hidup ini layak” terus bergulir.
“Jika televisi kumatikan, berita itu pun ikut hilang, tapi hidupku ini terus berlangsung. Tak mungkin hilang. Berpikir demikian, aku serta-merta nyaris berteriak sekencang-kencangnya, lantas menahan diri dengan susah payah, berusaha meyakinan diriku sendiri bahwa bagaimanapun juga situasiku barangkali masih mendingan.”—(hal. 67).
Tokoh aku juga kerap memikirkan makna dan kelayakan atas hidup dalam keadaan sendiri. Bahkan ia sempat berpikir bahwa segala perundungan ini bermula dari matanya yang juling. Singkatnya, tokoh aku selalu mempertanyakan apakah semua ini bermakna dan untuk apa hidup.
Lain halnya dengan Kojima. Ia dirundung karena keadaannya yang memprihatinkan; pakaian tidak rapi dan dianggap menjijikkan. Namun dalam keterundungan tersebut, Kojima memilih untuk menganggap bahwa semua hal memiliki makna dan maksud tersendiri. Kojima lebih memilih untuk menerima keadaan dan mengatakan bahwa kekuatan timbul dari penerimaan atas kelemahan diri.
“Mungkin… ada hal-hal yang maknanya bisa dipahami selama hidup… dan mungkin ada hal-hal yang baru bisa dipahami setelah mati dan orang lantas berkata seperti, ‘Oh, ternyata begitu….’
Lagi pula kapan sesuatu bisa dipahami itu tidak begitu penting, yang penting adalah bahwa penderitaan dan kesedihan begini pasti ada maknanya.”—(hal. 84).
Percakapan-percakapan filosofis dan reflektif semacam itu akan banyak kita dapatkan dalam novel ini. Hal tersebut kadang membuat saya termangu, apakah anak berusia 14 tahun sudah bisa berpikir sefilosofis itu? Tapi bisa jadi memang demikian adanya. Pasalnya, mereka menjadi penyintas dari perundungan dan telah bertungkus lumus bersama penderitaan sepanjang harinya.
Salah satu yang paling mindblowing sekaligus highlight dari novel ini terletak pada bagian ketika tokoh aku berani menanyakan kepada Momose (salah satu pelaku perundungan) tentang mengapa selama ini mereka melakukan perundungan. Bahkan si tokoh aku juga mengutarakan kepada Momose bahwa ia juga berpikir untuk bunuh diri sebab sudah lelah merasakan penderitaan yang tertanggungkan ini.
Alih-alih merasa jera, pelaku perundungan justru memberikan jawaban yang tak terduga. Pertama, ia menguraikan bahwa siapa pun perlu melindungi diri sendiri karena apa yang dilakukan orang lain pada diri sendiri tak dapat dikontrol.
Kedua, sekolah merupakan sistem untuk membedakan tinggi rendah kemampuan secara jelas dalam waktu tertentu. Orang yang kuat senantiasa akan menguasai yang lemah. Ketiga, hidup tak bermakna, maka manusia akan menciptakan maknanya sendiri. Oleh karena itu Momose mengatakan pada tokoh aku agar melindungi diri sendiri sebab ia yakin hanya itu satu-satunya jalan.
Terakhir, Momose meyakini bahwa manusia hidup berdasarkan seleranya masing-masing, sehingga orang bisa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang ia inginkan.
Uraian tersebut membuat tokoh aku menjadi tercengang. Ia menjadi gamang dan kembali bergulat tentang apa yang harus ia perbuat, apa makna hidup, apakah hidup ini seterusnya adalah penderitaan.
Namun satu hal yang penting digarisbawahi adalah percakapan tersebut merupakan sudut pandang anak berusia 14 tahun, sehingga ada satu kritik besar yang tersirat dari novel tersebut: bagaimana sistem pendidikan mengajarkan bahwa perundungan dan dominasi bagaimanapun adalah hal yang salah. Hal demikian menjadi PR besar bagi pendidik dan lembaga pendidikan untuk menanamkan pola pikir adil sejak dalam pikiran pada para siswa agar pola pikir seperti Momose tersebut tak terbentuk pada siswa-siswi yang lain.
Ciri khas Kawakami dalam novel ini tak luntur sedikit pun. Adalah kejujurannya menampilkan hal-hal pahit dan tabu itulah yang menjadi kekuatan novel ini. Keberaniannya mendobrak kemapanan, serta gaya penceritaan yang sederhana namun membekas. Barangkali novel Heaven ini perlu dibaca, bahkan jika perlu, dianjurkan untuk siswa-siswi dan juga bagi para pendidik agar turut mengalami apa yang dialami penyintas—meski hanya dalam pikiran sekali pun.[]
_________________
Data Buku
Judul : Heaven
Penulis : Mieko Kawakami
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
Tahun Terbit : 2023
Penerjemah : Ribeka Ota
ISBN : 9786231341181
Tebal : 240 Halaman