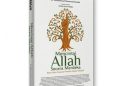Dulu mungkin nongkrong, sunmor, travelling, dan sebagainya adalah kegiatan menghabiskan waktu yang paling menyenangkan. Bagaimana tidak, kita bisa bertemu banyak orang, menyapa burung camar, hingga bisa jalan-jalan dengan pacar. Tapi, ada pula manusia yang harus terkungkung dalam bilik kamar dan memilih untuk tidak keluar rumah. Salah satunya ya saya.
Dalam benak ingin rasanya bisa jalan-jalan, main sama teman ke kota sebelah, menjelajahi alam pergi ke sawah-sawah, atau hal semacamnya lah. Yang penting keluar rumah. Namun, karena terbiasa dengan magnet kasur di rumah, menjadikan keinginan hati kecil saya ini harus mengalah. Saya yakin, yang pernah mengalami ini pasti tidak hanya saya saja.
Hingga suatu ketika saya dipaksa keadaan untuk merantau ke Jogja. Betapa ketar-ketirnya orang tua bahwa anak perempuan bontotnya ini akan pergi jauh dari mereka. Merantau sendiri di kota yang tak ada sanak keluarga sama sekali.
Takut. Kata yang sempat terbesit dalam hati.
Tapi, bukankah semakin kita menuruti rasa takut, maka kita akan dikalahkan oleh rasa takut itu sendiri? Bukankah semakin kita menghentikan langkah, maka semakin lama pula bagi kita untuk merekah? Jadi, sampai kapan kita menuruti rasa yang menjerumuskan kita pada hal yang itu-itu saja?
Untuk kalian yang mungkin sedang merasa seperti itu, jangan takut melangkah. Jangan takut keluar dari zona nyaman yang selama ini menyelubungimu. Keluarlah. Tapi, karena masih pandemi, ya entar-entar aja. Sabar. Hehe.
Balik lagi ke bacot ceritanya. Ibu saya berpesan bahwa, “Jangan terlihat seperti orang asing karena tak tahu jalan, tapi tetaplah terlihat tenang dan sok tahu jalan agar kamu tidak gampang dibodohi orang.” Tapi, ya kalau benar-benar nggak tahu ya tanya, Lur. Masa’ diem-diem bae.
Pesan itu yang selalu saya ingat ketika pergi ke beberapa tempat. Dari merantau inilah saya menemui banyak sekali pembelajaran. Mulai dari manajemen waktu, perhitungan uang, public speaking, sok asik, dan sebagainya. Pokoknya banyak. Hingga diriku ini menyadari bahwa hidup begitu menyenangkan ketika jalan-jalan. Tapi, kalau sakit, ya tetap aja ambyar.
Namun, aku bisa pastikan bahwa dunia perantauan tak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Selama kau temukan teman yang paham akan kantong keringmu, ya semua aman. Tapi, kalau salah pergaulan, ya begitulah. No comment.
Di perantauan pertama ini juga waktu pertama kalinya saya bertemu dengan Mbah Emha Ainun Nadjib. Dulu saya pernah berceletuk bahwa saya akan bertemu dengan beliau di Jogja. Dan Tuhan dengan kemurahan hati-Nya mengabulkannya.
Karena pertimbangan uang dan rasa sungkan kalau minta uang bulanan, akhirnya saya putuskan untuk jalan kaki menuju tempat Mocopat Syafaat diselenggarakan. Start-nya dari Jalan Kaliurang KM-5 bakda ashar. Sempat ingin membatalkan rencana jalan kaki ini, tapi balik lagi masalah uang. Jadi, ya sudah, diniatkan untuk belajar dan menikmati perjalanan.
Ada rasa takut juga mengingat bahwa saya ini perempuan dan berjalan hanya seorang diri. Ngenes. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Namun, ya sudah pasrah saja. Saya berdoa semoga Tuhan mengirimkan bala tentara-Nya untuk menjaga saya. Sok-sokan banget nggak tuh. Heuheuheu.
Tapi, betapa ajaibnya memang. Sepanjang perjalanan, Tuhan memudahkan langkah saya. Setiap kali ada laki-laki, hati udah was-was setengah mati. Namun, tiba-tiba laki-laki itu menunduk. Dan tidak hanya sekali, tapi semua yang saya temui memang menunduk. Aneh, kan? Saya juga masih berpikir itu aneh. Antara ini orang Jogja emang sopan semua atau ada sesuatu yang aneh dengan saya. Entahlah.
Sayangnya, niat saya ini tidak berhasil sampai tujuan. Karena saat itu bulan puasa, jadi saya harus mengakhiri langkah saya di Kadipiro. Istirahat sejenak dan berbuka lalu segera mencari masjid terdekat di sana. Siapa yang tahu bahwa tempat berakhirnya langkah saya adalah dekat dengan markas Kiai Kanjeng dan Mbah Nun. Hanya saja waktu itu saya belum begitu tahu tentang beliau, jadi ya nggak mampir.
Setelah selesai Magriban, nafas dulu, Lur. Capek habis jalan kaki. Kemudian, saya lanjutkan untuk naik ojol. Karena jarak sudah lumayan dekat, maka ongkosnya masih terbilang wajar. Jadi, gas aja naik ojol. Sempat bincang-bincang pula sama masnya di atas motor. Ternyata rumah neneknya dekat dengan lokasi. Jadi, udah tahu jalan tercepat sampai tujuan.
Di lokasi, saya bertemu dengan sahabat lama saya. Kami bersitukar banyak percapakan setelah beberapa bulan lamanya saling membungkam diri. Hingga tiba momen saya melihat wajah Mbah Nun. Melihatnya secara langsung, tidak lagi di layar televisi, maupun di layar handphone. Rasa capek saya seperti hilang menguap begitu saja.
Karena saya ini orangnya males ngomong–hingga dikira sombong–tapi justru karena itu saya bisa khusyuk duduk diam bersama dengan jamaah maiyah. Duh ayem rasanya. Sinau bareng dan bersholawat bareng dengan mereka. Kangen, Cuk. Pokoknya perjalanan saya selama merantau benar-benar tidak akan pernah saya lupakan. Sebab itu juga bagian dari proses kehidupan saya. Kemandirian saya dibentuk dari sana. Rasa takut saya hilang karenanya.
Jadi, kalau ditanya “Kok berani?” Ya kalau nggak berani, kita nggak akan belajar, Bos.
Akan seperti apa perjalanan kita itu tergantung keputusan seperti apa kita akan mengukirnya. Jika kita ukir untuk menapaki jalan lurus, ya mudah-mudah saja. Jika kita ukir untuk menapaki jalan bergelombang, ya butuh usaha dan kesabaran lebih. Kalau saya memilih mengukirnya dengan banyak jalan. Sehingga semakin mudah bagi saya menyesuaikan keadaan yang tidak senyaman ketika saya hanya berdiam tepekur di balik bilik kamar.[]